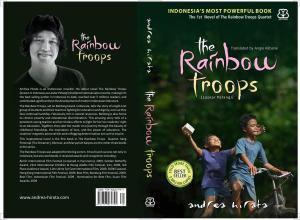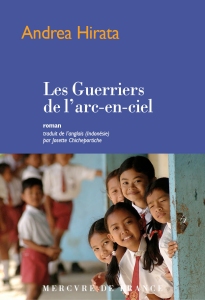Oleh: Wan Anwar
Perkenalan saya dengan hal ihwal Kendari masih amat terbatas. Dua kali menginjakkan kaki di Kendari (dan Raha) jelas tidak cukup untuk mengenal dan apalagi memahami Kendari (manusia, masyarakat, alam, sejarah, dan kebudayaannya). Meski demikian beberapa kenangan melekat dalam ingatan. Itu cukuplah membuat Kendari menjadi suatu tempat khusus dalam diri saya. Kenangan itu sebagian bersifat pribadi, sebagian lagi menyangkut kemasyarakatan dan kebudayaan.
Dua kali ke Kendari (sekali bersama rombongan Sastrawan Bicara Siswa Bertanya, sekali lagi bersama pelukis Herry Dim), masing-masing kurang lebih seminggu, telah mengenalkan saya pada banyak hal. Pengenalan yang paling menyenangkan tentu saja karena mendapati banyak kawan di Kendari yang intens menggeluti kesenian, khususnya teater dan sastra. Entah kenapa jika di suatu kota mendapati sejumlah orang menggeluti kesenian, hati ini sedikit tenteram. Selalu ada harapan, dengan adanya orang-orang berkesenian, maka “pembangunanisme”, modernisasi, dan gelegak globalisasi sedikit banyak akan “dikontrol”, dikritisi, dan bahkan dinegoisasi sehingga pembangunan tidak melulu berpijak pada percepatan ekonomi dan pembangunan fisik lainnya. Ini penting karena pembangunan seyogyanya mencakupi keutuhan dan keunikan manusia itu sendiri: darah-daging, lahir-batin manusia dan masyarakatnya.
Jika benar harapan di atas, berarti saya berpandangan bahwa kesenian (katakanlah teater dan sastra) adalah suara lain, mungkin ganjil dan kecil, yang memiliki daya untuk bernegoisasi dengan suara (budaya/kuasa) dominan yang seringkali menghegemoni keadaan. Suara dominan antara lain modernisasi atau globalisasi yang datang dari berbagai penjuru dunia, utamanya semangat kapitalisme dari negara-negara Barat. Saya katakan “antara lain”, karena suara dominan dapat saja berupa “ideologi pusat” bernama Jakarta, bahkan budaya tradisi yang tidak selalu berisi “kearifan-kearifan lokal”.
Suara dominan agaknya sudah menjadi “wataknya” sendiri melakukan kooptasi, hegemoni, dominasi yang pada ujungnya “penaklukan” pada suara-suara kecil yang disisihkan. Sebagai manusia/ masyarakat yang pernah mengalami pahit-getirnya penjajahan dunia Barat (kolonialisme), adakalanya kita melestarikan watak kolonial, selain tentu menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan. Sementara itu sebagai bangsa yang lahir dari keragaman budaya, bahkan keragaman kerajaan di masa lampau, tidak jarang kita mewarisi sifat chauvinis (membanggakan masa silam kerajaan/etnisitas) yang gilirannya menumbuhkan rasisme dan penindasan terhadap si liyan (the other). Oleh karena itu setiap suara dominan, dari manapun sumbernya, harus dikritisi bahkan dilawan.
Dapatkah kesenian, sastra dan teater khususnya, melawan suara dominan? Bukankah kesenian, hampir di manapun dan kapanpun, selalu menjadi suara sunyi yang kesepian? Dengan kata lain tidak dapat mengalahkan non-kesenian, katakanlah politik dan ekonomi?
Tentu saja kita tidak bicara soal “mengalahkan” melalui kerja kesenian karena ambisi mengalahkan bagian dari sifat penindasan. Kesenian, dengan suara sunyinya, beritikad untuk “menghilangkan” penindasan, sekurang-kuranya suara dominan dapat mempertanyakan kembali dominasinya. Selebihnya, suara dominan akan menghargai suara-suara sunyi terpinggirkan, melakukan interaksi intensif, dan pada gilirannya suara-suara sunyi terpinggirkan mampu turut serta membangun kompleksitas budaya dan masyarakat. Dengan kata lain interaksi suara dominan dan suara-suara terpinggirkan menghasilkan budaya kreatif dan produktif.
Tapi apa yang saya ketahui tentang Kendari? Suara dominan macam apa yang “menguasai” Kendari? Suara-suara terpinggirkan apa pula yang sedang berinteraksi, bahkan melawan, suara dominan?
Sekali lagi lagi pengetahuan saya tentang Kendari amat terbatas. Dalam dua kali kunjungan ke kota di Tenggara Sulawesi ini saya hanya tahu bahwa di Kendari ada banyak toko menjual makanan lezat biji jambu mente. Di beberapa titik lokasi teluk Kendari ada komunitas Bajo. Di teluk Kendari ada keramaian malam muda-mudi berkencan, restoran terapung, jalan-jalan lebar lengang di kanan-kirinya melayah hutan bakau, kapal-kapal jet-foil di Pelabuhan Kendari, warung remang-remang dengan musik hingar bingar, pasar Wua-wua di salah satu bagian kota, mini market dan supermarket, restoran-restoran fast-food, warung-warung tenda malam hari menjajakan sea-food, lalu lintas angkot berseliweran dengan mobil-mobil pribadi seperti di banyak kota di Indonesia umumnya, kampus luas tetapi asrama mahasiswanya kurang terurus, perumahan dosen di mana Ahid Hidayat tinggal, perusahaan tambang dan penyeberangan ke Makasar di Kolaka, pelabuhan fery di Tampo yang menghubungkan Kendari dengan Muna dan Buton. Ah apalagi ya? Pengetahuan saya tentang Kendari benar-benar terbatas.
Kadang menyesal mengapa sewaktu di Kendari tidak banyak “berpetualang” untuk mengetahui kekhasan Kendari. Saya belum sempat secara mendalam bertanya pada kawan-kawan mengenai empat etnis (Tolaki, Muna, Buton, dan Morunene) dominan di Kendari. Saya belum sempat bertanya sejarah, mitos, dan cerita-cerita rakyat Kendari. Saya belum tahu bagaimana lembaga adat menyelesaikan jika ada konflik antar-entnis atau sesama etnis. Meski saya bersyukur sedikit tahu bagaimana caranya orang luar Kendari kalau ingin meminang gadis Kendari.
Saya berharap bisa datang lagi ke Kendari. Selain untuk mengenal lebih jauh Kendari, saya juga ingin jalan-jalan ke Buton. Dari beberapa buku sejarah dan filologi, kesultanan Buton sering menjadi bahan pembicaraan, terutama dalam kontaknya dengan kerajaan di Makasar, Bima, kerajaan di Jawa dan Sumatera, dan kolonial Belanda di masa silam. Kontak-kontak yang selain menunjukkan awal modernisasi/ globalisasi, juga kontak-kontak menyangkut negoisasi (perkawinan putra-putri antar-kerajaan misalnya) untuk menghindar konflik dan perang (meski konflik dan perang terjadi juga). Semua itu agaknya penting untuk lebih mengenal, menghayati, dan memahami Kendari.
Tapi saya beruntung sempat menyeberang ke Raha/ Muna, meskipun saya iri kepada penyair Cecep Syamsul Hari yang begitu tiba di Raha sebuah sajak berjudul “Raha” lahir dari tangannya. Oleh pemilik hotel (hotel yang sebenarnya rumah) di Raha saya diantar ke sebuah desa, malam-malam, untuk melihat kain tenun khas Muna. Pada kedatangan kedua, saya lebih beruntung karena sepanjang malam ditemani Gani, Roy, dan Inal (yang pertama seniman Kendari asal Mandar, yang lainnya seniman Raha) jalan-jalan ke pantai/ pelabuhan Raha. Bersama mereka saya menikmati lampu-lampu neon berderet sepanjang pelabuhan, menikmati debur ombak pelahan, serbuan angin laut, dan kesibukan malam pelabuhan. Mereka bicara banyak tentang Muna, meski sebagian tak terekam dalam ingatan. Mereka bercerita tentang tugu pembatas Raha, tentang kebersahajaan seorang ibu tokoh politik di negeri ini, tentang kontu kowuna (batu berbunga), tentang rencana pembangunan hotel di tepi pantai menjelang PORDA, tentang sumber minyak di bawah tanah Raha, dan tentang penebangan kayu jati yang terus berlangsung hingga kini.
Ah kayu jati? Dengan sedih malam itu saya saksikan bagaimana truk-truk mengangkut kayu jati yang sudah diikat rapi dan langsung dimasukkan ke kapal-kapal yang akan menyeberangkannya entah kemana. “Kayu jati Raha kualitasnya nomor wahid,” begitu kata Roy. Saya terhenyak sejenak: kayu jati, nomor wahid! Betul-betul spiritual: kayu jati kayu yang hebat (makanya kita menggunakan ungkapan “jati diri” untuk mengungkapkan etos bangsa) dan wahid bukankah ahad (satu)? Pulau Muna ini pulau yang menyimpan “jati” kualitas ahad! Tentu tak elok jika penggerogotan atasnya (baik alam maupun kebudayaan) dibiarkan. Pada kesempatan ini saya ingin meminta sesuatu pada Roy dan Inal: jaga pulaumu dengan seluruh dayamu. Dapatkah kesenian berperan dalam hal ini?
Pada sebuah pagi, Roy dan Inal mengantar saya ke Pasar Raha. Sebuah kehidupan cukup ramai dibandingkan jalan-jalan kota Raha yang lengang dan lebih banyak dilintasi sepeda motor. Wa Ode Erawaty, gadis Raha yang juga menemani, mampu membuat sejuk kota Raha yang panas. Kulitnya yang putih kehitaman seperti kulit roti tak matang di pembakaran: mengingatkan saya pada sebuah film Prancis yang tokohnya (orang kulit putih) ingin berkulit coklat sebagai bentuk negoisasi budaya terhadap tempat tinggalnya: sebuah kota di Amerika Latin, bekas jajahan Prancis!
Penyeberangan ke Raha (sekali melalui Tampo, sekali lagi melalui pelabuhan Kendari) juga menyimpan kenangan. Dari laut lepas yang tidak terlalu keras ombaknya dapat terlihat bagaimana indahnya tepi-tepi Sulawesi Tenggara. Di selat cempedak ombak memang membuat jantung agak berdetak, tetapi pada saat itulah tercipta sebuah sajak:….jantung berdetak di selat cempedak/ pulau-pulau meminta untuk kudekap/ superjet melaju ke laut biru/ memburu yang kita tuju…(2004)
Apa yang kita tuju? Siapakah “kita”? Pada saat itu yang ada: saya, Era, dan Gani, selebihnya penumpang lain. Tapi dalam konteks tulisan ini, izinkan saya memaknainya secara lain: apa yang kita tuju dengan berkesenian, entah itu berteater atau bersajak sebagaimana dilakukan kawan-kawan yang dihimpun Teater Sendiri ini?
***
Betapa senang ketika Syaifuddin Gani mengirim sms kepada saya yang intinya meminta saya mengantari sajak-sajak yang diantologikan menjadi buku Sendiri 3. Buku ini akan diluncurkan/ dibacakan dalam pembukaan Festival Teater Pelajar (FTP) Se-Sulawesi Tenggara dalam rangka 14 tahun Teater Sendiri yang diasuh Achmad Zain, sebuah kelompok teater yang aktif mementaskan garapannya, baik di kota Kendari, Sulawesi Tenggara umumnya, Makasar, Banjarmasin, Samarinda, Surabaya, Yogyakarta, maupun Jakarta. Sesuai namanya, meski mungkin “sendiri”, mereka terus berproses, sebagaimana ditekadkan Achmad Zain melalui sajaknya: Din/ melangkahlah selama kaki kanan/ dan kaki kiri belum menyatu (sajak “Sembilan Anak Tangga”). Ungkapan sederhana yang mengejutkan, sekaligus simbolik mengingat judul “Sembilan Anak Tangga” mengisyaratkan keharusan tuntasnya menempuh perjalanan untuk mencapai tangga sepuluh: dan di puncak tangga ada cahaya membias/ biarkan menerpa wajah kita. Sejenis puncak pencerahan atau spiritual hasil proses perjalanan yang akan menjelmakan “jati diri” para pejalan budaya.
Pengalaman dua kali menikmati Kendari (dan Raha) ternyata tidak sama dengan pengalaman membaca lebih dari 100 sajak dari 11 penyair dalam buku ini. Itu adalah bukti bahwa Kendari dalam pencerapan saya adalah segugus versi dan Kendari yang direspons/ dihadirkan 11 penyair adalah versi yang lain. Keberagaman pencerapan, juga tafsir, amat tergantung pada pengetahuan dan pengalaman setiap orang, baik secara kuantitatif maupun terutama kualitatif. Setiap individu adalah perspektif dan karena itu akan melahirkan gambar yang beragam. Dari asumsi ini saja sudah muncul keharusan berkomunikasi, bahkan bernegoisasi, dalam merespons hal-ihwal yang hadir baik secara diakronis (perspektif waktu) maupun sinkronis (perspektif ruang). Uraian ini tidak lain sebentuk komunikasi dan negoisasi dalam perspektif ruang dan waktu pencerapan.
Negoisasi budaya niscaya tak terelakkan. Pengalaman-pengalaman pahit di masa silam (sejarah) karena ulah kolonialisme dan kenyataan kini yang jauh dari harapan adalah kontradiksi yang menuntut negoisasi. Sekurang-kurangnya respons bila solusi belum mungkin dilakukan. Lagi pula sajak tidak ada urusan dengan solusi, jika pun ada biarlah pembaca yang bicara. Kontradiksi itu sering membuat para penyair gelisah sebagaimana diungkapkan Syaifuddin Gani dalam “Langit Tak Terjangkau” yang merespons Losari (pantai di Makasar): sepanjang losari/ kau sabdakan cerita-cerita silam/ dan kau tikamkan lagu asing…..dan si mata biru itu/ telah lama berlalu// suatu saat aku akan datang lagi, katanya/ tak lagi memanggul senjata/ tapi mendulang sejarah dan pusaka.
Negeri ini memang sudah merdeka, tapi apakah betul merdeka sebenar-benar merdeka? Tentu belum. Selain beragam kuasa dari berbagai belahan penjuru dunia terus mengintai, kita juga harus berhadapan dengan para penindas dari negeri dan lingkungan sendiri. Kau lirik dalam sajak di atas bereaksi atas keasingan di kotanya:…kalau kau datang, kuberondong kau/ dengan sebilah siri’/ katamu, sambil pasakkan pagar dan pugar. Cukup tegas bahwa kuasa lokal, mungkin kearifan lokal (siri’) dalam sajak itu dihadapkan pada suara dominan (modernisasi/ globalisasi yang berbau Barat) yang representasinya “anak dara berbaju bodo/ menari di atas panggung” di tengah “kecapi yang merintih dan teriris”.
Dalam cara berpikir dikotomis atau oposisi biner adalah lumrah bila hitam dihadapkan pada putih, tradisi ditentangkan pada modernisasi. Akan tetapi kuasa dominan tidak selalu datang dari Barat dan tradisi tidak selalu menjadi harapan. Sering muncul kebimbangan dan persoalan di sini. Meski dengan sajak yang anasirnya kurang terjaga, dalam sajak “Kekalahan Dini Hari” Sendri Yakti mengungkapkan persoalan itu: Malam marut, kata-kata mengerucut/ menerobos sejarah yang menggumuh di sudutsudut/ di udara merambat musik bingar, igau yang riuh/ percakapan jadi liat dan menoreh pedih/ sudah kulupa, kapan negeri ini merdeka…. kita berdebat tentang feodal yang kataku belel/ tapi masih kau panggil ayahmu ode/ tak seperti kudecak lidah/ dan memanggil kucingku sultan…
Dua sajak di atas, meski bukan sajak terbaik dari kedua mereka, melukiskan situasi masyarakat poskolonial, di mana sisa kolonialisme masih mengganjal, modernisasi dan globalisasi tak bisa membuat manusia tentram, tetapi pada saat bersamaan tradisi lokal belum mampu menaungi manusia dalam rasa betah. Kembali ke tradisi lokal belakangan dianggap sebagai jalan untuk menyikapi keadaan. Tentu saja bukan tradisi asal tradisi, melainkan kearifan lokal yang dapat membantu menyelesaikan banyak soal kehidupan dewasa ini yang kian kompleks. Sayangnya seperti diungkapkan Irawan Tinggoa tradisi sebatas ritus belum dapat berbuat banyak. Perhatikan sajak “Ritus Mosehe”, terutama bait terakhir: sepejam mata/ taawu dihunuskan:/ kerbau putih sebagai tumbal/ darahnya bercecer mengusir sesal/ ia lemas telah mengusir tikai/ yang tak padam.
Di antara penyair dalam buku ini, Irawan Tinggoa menunjukkan hasrat besar merespons banyak soal dengan pendekatan tradisi lokal. Sekurang-kurangnya banyak istilah-istilah lokal dibaurkan ke dalam komposisi sajaknya yang cukup lancar mengalir. Kepekaannya pada momen dan hasratnya untuk “mengucapkan” tradisi berpotensi untuk melahirkan sajak sederhana tetapi mendalam. Responsnya terhadap suasana kota terasa sederhana dan jenaka: selokan kota gerah berpenuh cena/ di tepi-tepi rumah kumuh membuncah// mengepul bau kemenyan/ menebar aroma kematian// seorang dukun kota/ sesaat meringis diserang bala diare (sajak “Kota”).
Hiruk pikuk kota siang malam di banyak daerah di negeri ini sering menjadi tema dan kegelisahan para penyair ketika memaknai diri dan kehidupan di sekitarnya. Memang kontradiksi (harapan dan kenyataan berbeda) adakalanya menarik direspons dengan sederhana dan jenaka sebagaimana dilakukan Irawan dalam sajak “Kota” di atas. Lihat pulalah sajak Karmil Edo Sendiri yang berjudul “Gelap”. Sajaknya yang merespons kota dimainkan lincah dengan wacana Edison (penemu listrik) dan Einstein (penemu teori relativitas) dalam ikatan persoalan gelap dan terang keadaan. Bait akhir sajak ini jelas merupakan kritik terhadap perilaku sebagian masyarakat yang suka melakukan “transaksi” di “tempat gelap”.
Saya tidak tahu apakah di Kendari dan sekitarnya ada tradisi lisan yang mengandalkan kekuatan irama dan bunyi kata. Yang jelas Didit Marshel tampak kuat memainkan irama dan bunyi kata-kata, sebagian mirip pantun bahkan mantra, meski pada sebagian sajak terasa dipaksakan. Kekuatan memainkan irama dan bunyi kata tampak tegas dalam “Negeri Batu” misalnya. Banyak kata batu yang tentu bukan sembarang batu digunakan Didit untuk mengkritisi kehidupan kita sekarang yang memang sudah membatu. Sebuah keadaan yang meminta dipecahkan, oleh sejenis “kapak” (idiom Sutardji Calzoum Bachri) atau oleh benda khas di lingkungan Kendari dan sekitarnya.
Sajak pada umumnya memang suara lain, suara aneh yang ganjil, yang sunyi dan kesepian, di tengah riuh kota, manusia dan masyarakat batu yang berkata-kata bukan atas kesadaran. Suara penyair dikekalkan dalam kata. Dan kata, sebagaimana diungkapkan Irianto Ibrahim, meski diambil oleh orang tidak akan pernah kehilangan hakikatnya. Bacalah “Sajak untuk Dhani” yang menghidupkan kata-kata dalam permainan dan renungan:…Tetaplah bersama kata/ Biarkan ia tumbuh dan tegak berdiri/ Ketika satu orang mengambil satu daunnya/ tidak berarti ia kehilangan nama pohonnya.
Kata, itulah harta penyair yang paling berharga. Jika penyair kehilangan kata, habis sudahlah eksistensinya. Itu sebabnya setiap saat penyair bergulat dengan kata. Tentu saja bukan semata bermain sekedar memainkan kata-kata, melainkan menggali kemungkinan kata-kata. Ironisnya sekarang ini penyair hidup di masyarakat yang nyaris kehilangan kata-kata. Benda-benda telah menggantikan komunikasi sehari-hari. Benda-benda merebut posisi kata sebagai citra. Benda-bendalah yang kini menjadi citra: rumah, mobil, handphone, pakaian, dan benda-benda produk industri lainnya. Teater mutakhir di negeri ini, juga di dunia, menyikapi kenyataan ini dengan menghadirkan pergelaran tanpa kata-kata. Teater kembali ke akarnya semula: tubuh dan segala kemungkinan potensi tubuh.
Lalu apa yang akan dilakukan penyair ketika kata telah direbut iklan dan retorika politik? Haruskan kita hanya dan hanya berkawan sunyi sebagaimana diungkapkan Iqbal Oktavian dalam sajak “Bersama Kesunyian”? Atau “kita hanya kuasa/ menunggu kapan saat itu tiba/ di mana waktu berhenti/ dan kita ditagih pertanggungjawaban/ sang waktu (sajak “Perjalanan Waktu” karya Tongis Alamsyah)? Dan karenanya kita tak perlu melakukan apa-apa karena kata yang kita cipta akan sia-sia, karena waktu dan tempat kita berdiam telah melakukan segalanya, dan kita cukup “melekat pada tubuhmu” (sajak “Kota Muna” karya Royan Ikmal”). Dan kemudian alam memberi musibah karena kita melalaikannya seperti diungkapkan Royan Ikmal dalam “Syair Muna yang Terbang”?
Saya kira saya tak perlu pesimis. Meski sajak-sajak para penyair di buku ini lebih banyak menyampaikan gambaran muram, tetapi kesetiaannya untuk terus berkata-kata membuat saya cukup optimis. Kesanggupan mereka bertahan di “negeri batu” dan keriangan mereka “memainkan” kata-kata tentu menambah optimisme saya. Pasti saya akan lebih optimis jika mereka lebih serius belajar membaca dalam pengertiannya yang luas, lebih khusuk mempelajari masa silam dan masa kini, baik di Kendari maupun di luar Kendari.
Masalah penyair tentu bukan sekedar kata-kata. Jika kata-kata itu representasi kehidupan, interaksi kehidupan, dan unsur pembentuk kehidupan, maka persoalan mendasar penyair adalah kehidupan itu sendiri. Menyelami kehidupan tidak selalu harus melulu langsung, melainkan bisa melalui kata-kata para penjelajah kehidupan. Untuk memuliakan kata-kata, seorang penyair dapat memulainya dengan serius membaca karya-karya penyair lain dalam bentangan sejarah sastra Indonesia, sejarah sastra dunia, bahkan sejarah sastra di Kendari dan sekitarnya.
***
Secara jujur harus dikatakan, sejauh terlihat dari sajak-sajak dalam buku ini, pergulatan para penyair selayaknya diintensifkan. Pada sejumlah sajak mereka tidak jarang masih terdapat kelemahan dasar komposisi yang mungkin disebabkan karena belum utuhnya pengalaman puitik, belum pekanya pada kata-kata, belum tajamnya menciptakan ungkapan segar, atau belum terlatih mengontrol logika imajinasi yang membuat anasir sajak tidak saling mendukung makna atau kegelisahan penyairnya. Adakalanya pula hasrat untuk menyampaikan sesutu terlalu kuat sehingga baris/ bait sajak menjadi pengap oleh kata-kata abstrak.
Menulis sajak barangkali ibarat mendaki puncak. Pada awalnya kita berjalan di keriuhan banyak orang, berkawan kata-kata klise, lalu memasuki kampung-kampung sunyi, pematang-pematang lengang, lembah yang membuat hati gelisah, rumpun-rumpun rimbun di mana hanya ada satu dua orang melintas, menaiki tebing terjal atau licin, berkenalan dengan akar dan juntaian pohon-pohon besar, gelap dan dingin, matahari tak terlihat, bulan entah di mana, hingga akhirnya sampai di puncak setelah pori-pori tubuh meneteskan jutaan keringat.
Atau seperti menuju samudera dengan gelombang tak terkira. Pada mulanya kita bertamasya saja di bibir pantai, berenang di tepian, agak ke tengah dan mulai merasakan gelombang di permukaan dan kedalaman, terus berenang ke tengah hingga akhirnya menyatu dengan samudera di mana segala jenis karang, gelombang, ikan, topan, dan badai lautan menjadi bagian diri dan kehidupan.
Baik dalam mendaki puncak maupun menembus samudera, perkara latihan tentu penting. Akan tetapi keberanian memasuki pahit-getir kehidupan dan kejujuran mengungkapkan kepada orang lain tidak kalah pentingnya. Mungkin kita tidak menjadi apa-apa, tidak menjadi pahlawan atau pujaan, tidak diberi hadiah seperti para pendaki gunung atau peloncat indah dan perenang dalam perlombaan. Akan tetapi kita telah berdialog dengan mereka, dengan yang menjangkau samudera di atas kapal atau melihat puncak dari helikopter: meyakinkan mereka bahwa kata, suara lain yang aneh dan ganjil itu, bisa “sekuasa” benda-benda. Itulah kira-kira negoisasi budaya.
Selamat berulangtahun Teater Sendiri. Karena engkau telah “bernegoisasi” dengan berbagai suara, termasuk suara dominan, di Kendari, percayalah diri engkau tidak akan pernah sendiri. ***
Cipocok-Serang, 15 Agustus 2006
Pukul 01.16 WIB
Wan Anwar, penyair dan esais. Bekerja sebagai editor di majalah sastra Horison dan sebagai dosen di FKIP Untirta Banten. Bukunya yang sudah terbit: Sebelum Senja Selesai (2002), Sepasang Maut (2004), dan Kuntowijoyo dan Dunianya (2006). Tinggal di Cipocok-Serang, Banten.