RUBRIK BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA HARIAN RAKYAT SULTRA-KANTOR BAHASA PROV. SULTRA
Category Archives: Uncategorized
Rubrik Bahasa, Sasatra, dan Budaya Kerja Sama Antara Kantor Bahasa Prov. Sultra dan Harian Rakyat Sultra
Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara berkerja sama dengan Harian Rakyat Sultra, membuka rubrik Bahasa, Sastra, dan Budaya di Harian Rakyat Sultra setiap hari Sabtu, mulai 6 Februari—24 Desember 2016. Rubrik tersebut dibagi atas empat kolom yakni puisi, cerpen, esai/artikel, dan info lingua. Khusus rubrik Info Lingua, hanya dapat diisi oleh staf teknis Kantor Bahasa Prov. Sultra, sedangkan tiga rubrik lainnya terbuka untuk umum. Adapun ketentuan pengiriman naskah, sebagai berikut:
1. Rubrik Bahasa, Sastra, dan Budaya akan terbit setiap hari Sabtu pada setiap bulan
2. Setiap naskah yang ditulis bukan karya terjemahan, saduran, dan tidak mengandung unsur plagiasi
3. Naskah dikirim ke pos-el: bastra.kbsultra@gmail.com
4. Setiap naskah belum pernah dipublikasikan di media cetak dan internet
5. Naskah esai/artikel berisi hal-hal yang berkaitan dengan masalah kebahasaan atau kesastraan
6. Untuk rubrik puisi dan cerpen dalam setiap bulannya akan memuat tiga atau empat kali karya penulis Sulawesi Tenggara, sedangkan satu kali pemuatan diperuntukkan bagi penulis dari luar Sulawesi Tenggara
7. Naskah esai/artikel antara 5000—5500 karakter disertai biodata singkat
8. Naskah cerpen antara 7500—8500 disertai biodata singkat
9. Naskah puisi antara 5—10 judul disertai biodata singkat
10. Naskah yang dimuat akan menerima honorarium dari Kantor Bahasa Prov. Sultra dan bukti pemuatan dalam bentuk file PDF
11. Secara teknis, naskah yang masuk akan diterima oleh panitia lalu akan dihilangkan nama penulisnya. Selanjutnya, naskah tersebut akan dikirim ke masing-masing redaktur untuk dibaca, diseleksi, dan ditentukan pemuatannya.
12. Naskah yang dinyatakan dapat dimuat olek redaktur akan dikirim kembali ke panitia. Selanjutnya, panitia akan mengembalikan nama penulisnya. Proses selanjutnya yaitu memasuki tahap lay out oleh pihak Harian Rakyat Sultra untuk kemudian diterbitkan.
13. Setiap rubrik memiliki redaktur, untuk rubrik esai/artikel dan info lingua dari pihak Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk rubrik puisi adalah Cecep Syamsul Hari, dan untuk rubrik cerpen oleh Raudal Tanjung Banua
14. Hal lain yang belum termaktub di ketentuan ini, akan dijelaskan kemudian.
PANITIA
Empat Karakter Tokoh Dongeng Buton “Wa Ndiundiu”: Sebuah Pembacaan Psikoanalisis Sigmund Freud
SUMBER:
METASASTRA (JURNAL PENELITIAN SASTRA)
ISSN: 2085-7268. Volume 8, Nomor 1, Juni 2015. Halaman 121—138
Diterbitkan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat
EMPAT KARAKTER TOKOH DONGENG BUTON “WA NDIUNDIU”: SEBUAH PEMBACAAN PSIKOANALISIS
SIGMUND FREUD
Four Characters on Butonese Fairytale Wa Ndiundiu:
A Sigmund Freud Psikoanalysis Interpretation
Syaifuddin
Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara
Jalan Haluoleo, Kompleks Bumi Praja, Anduonohu, Kendari
Ponsel: 085247877676, Pos-el: syaifuddingani@gmail.com
Naskah Masuk: 5 Maret 2015, disetujuai: 11 Mei 2015, revisi akhir: 25 Mei 2015
Abstrak: “Wa Ndiundiu” adalah dongeng yang dibangun melalui pergumulan karakter tokohnya. Setiap tokoh menampilkan watak sesuai kondisi kejiwaannya. Psikologi sastra adalah kajian yang memandang sastra sebagai aktivitas kejiwaan pelakunya. Permasalahan penelitian adalah bagaimanakah struktur kepribadian, kecemasan, dan klasifikasi emosi empat tokoh Wa Ndiundiu? Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan empat karakter tokoh Wa Ndiundiu, menggunakan teori Psikoanalisis Sigmund Freud. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Penulis menganalisis data dengan pendekatan tekstual, mengkaji aspek psikologisnya. Hasil penelitian menunjukkan tokoh Ayah adalah akumulasi karakter yang diliputi kecemasan, tanatos, dominasi id, kemarahan, kebencian. Wa Turungkoleo memiliki cinta, kesedihan, eros. Kecemasan terkendali oleh ego dan superegonya. La Mbatambata dikuasai alam bawah sadar dan fase id, muasal dorongan primitif yang belum dipengaruhi kebudayaan. Tokoh Wa Ndiundiu menghimpun beragam kerumitan kejiwaan. Antara id, ego, dan superego saling bersitegang pada jiwanya. Tiga kecemasan, eros dan tanatos, hadir sekaligus dalam dirinya. Beragam klasifikasi emosi mengelucak dan memengaruhi tindakannya.
Kata Kunci: Dongeng, Karakter, Wa Ndiundiu, Psikoanalisis Sigmund Freud
Abstract: Wa Ndiundiu is a kind of folktale which builds through the struggle of its characters. Every character show some characterizations which related with psychological problem. Psychology was used to describe psychological fact of its characters. The problem which describe in this article is the activity of four characters in this folktale, they are structure of personality, anxiety, emotional classification. The objective of this article is describing the personality of four characters in this folktale by using Sigmund Freud Psychoanalysis. This article using descriptive qualitative method and textual approach. The result of the analysis show that the first character “Ayah” is a character with anxiety, tanatos, id, madness, and hateness. The second character “Wa Turungkoleo” is a character that has love, sadness, and eros. His anxiety can be controlled by her ego and super ego. The third character, La Mbatambata is still driven by his subconscious mind and id phase as a place of primitive stimulus which is influenced by the culture. The fourth character, Wa Ndiundiu collects the entire psychological situation in her characterization. Three types of anxiety, eros, and tanatos have been existed in her characterization. Many types of emotional feeling has been disturbed in her mind and influenced her action.
Keywords: Folktale, Character, Wa Ndiundiu, Sigmund Freud Psychoanalysis
1. Pendahuluan
Dongeng adalah salah satu jenis cerita rakyat atau sastra lisan yang penuturannya disampaikan secara berkisah yang bersifat prosa. Sebagai kisah yang dimiliki secara kolektif, sastra lisan atau dongeng bukanlah hasil ide satu orang, tetapi mungkin berasal dari masyarakat yang diangkat oleh seseorang berkat ketajaman penghayatannya (Rusyana dalam Amriani, 2011:304). Sementara itu, menurut Danandjaya dongeng adalah cerita prosa rakyat yang tidak dianggap benar-benar terjadi. Selanjutnya dikatakan bahwa dongeng diceritakan terutama untuk hiburan, walapun banyak juga yang melukiskan kebenaran, berisikan pelajaran (moral), atau bahkan sindiran (1994: 83). Selain dapat menghibur, dongeng dilahirkan terutama sebagai medium penyampai nilai yang hidup di masyarakat pendukungnya.
Dongeng dapat dinikmati sebagai karya sastra yang dibangun melalui pergumulan karakter atau tokoh-tokohnya. Dengan kata lain, membaca dongeng adalah membaca setiap gerak dan sifat karakter yang menghidupkan cerita. Setiap karakter menampilkan berbagai watak dan perilaku yang terkait dengan masalah kejiwaan dan pengalaman psikologis atau konflik, sebagaimana yang dialami manusia dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, psikologi memiliki peran di dalam mengungkap fakta kejiwaan para tokohnya.
Psikologi sastra adalah kajian sastra yang memandang karya sastra sebagai aktivitas kejiwaan. Karya sastra dipandang sebagai fenomena psikologis, akan menampilkan aspek kejiwaan melalui tokohnya jika teks yang dikaji berupa drama maupun prosa. Dengan demikian, asumsi dasar penelitian psikologi sastra dipengaruhi, setidaknya dua hal. Pertama, adanya anggapan bahwa karya sastra merupakan produk dari suatu kejiwaan dan pemikiran pengarang pada situasi setengah sadar (subconcious) setelah jelas baru dituangkan ke dalam bentuk secara sadar (conscious). Antara sadar dan tidak sadar selalu mewarnai proses imajinasi pengarang. Kedua, kajian psikologi sastra selain meneliti perwatakan tokoh secara psikologis juga aspek pemikiran dan perasaan pengarang (Endraswara, 2003: 96).
“Wa Ndiundiu” adalah sebuah dongeng yang hidup di masyarakat Buton, memperlihatkan pergulatan psikologis setiap karakter tokoh yang kompleks dan unik. Sehingga tingkah laku, respon, dan sikap setiap tokoh adalah pengejewantahan kondisi psikologis yang bersemayam di dalam dirinya. Dengan demikian, memelajari atau menerapkan analisis psikologi sastra sebenarnya sama dengan memelajari manusia dari sisi dalam.
Dongeng “Wa Ndiundiu” menjadi sangat relevan dan penting didekati dalam pembacaan psikologi karena lebih memberi kesempatan untuk mengkaji lebih dalam aspek psikologis tokohnya. Selain itu, untuk membuktikan bahwa karya sastra, khsusunya Wa Ndiundiu, memiliki aspek kejiwaan yang sangat kaya dan khas. Dengan demikian, setiap tindakan yang dilakukan oleh tokoh-tokohnya tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kondisi kejiwaan yang melekat padanya.
Pengkajian psikologis sastra tentunya berangkat dari aspek sastrawi sebuah karya sastra itu sendiri. Itulah sebabnya, tokoh menjadi fokus utama di dalam penelitian karena dari sosoknyalah aspek-aspek kejiwaan yang mengemuka di dalam karya sastra, melekat dan termanipestasikan. Pada titik ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Minderop (2011:3) bahwa terkait dengan psikologi, terutama psikologi kepribadian, sastra menjadi suatu bahan telaah yang menarik karena sastra bukan sekadar telaah teks yang menjemukan tetapi menjadi bahan kajian yang melibatkan perwatakan/kepribadian para tokoh rekaan, pangarang sastra, dan pembaca
Untuk penelitian mengenai dongeng “Wa Ndiundiu” dari aspek psikologis, penulis menggunakan teori Psikoanalisis Sigmund Freud yang menitikberatkan analisis pada fungsi dan perkembangan mental manusia. Teori psikoanalisis Sigmund Freud sangat relevan dengan kondisi dan pergumulan psikologis keempat tokoh di dalam Dongeng Wa Ndiundiu. Keempat karakter tokoh yaitu Ayah, Wa Ndiunidu (Ibu), Wa Turungkaleo (kakak), dan La Mbatambata (adik) adalah empat sifat yang kini terus-menerus dikenang masyarakat Buton sebagai ingatan kolektif yang tidak dapat dilepaskan dari kenyataan geografis dan kultural Buton.
Secara skematis Sigmund Freud mengambarkan jiwa sebagai Gunung Es. Bagian yang muncul di permukaan air merupakan bagian terkecil yaitu puncak dari Gunung Es itu yang dalam hal kejiwaan adalah bagian kesadaran (conciousnes), agak di bawah permukaan adalah bagian prakesadaran (sub conciousness) dan bagian terbesar terletak di dasar air yang dalam hal kejiwaan merupakan alam ketidaksadaran (unconciousness). Sehingga dapat dikatakan bahwa kehidupan mausia dikuasai oleh alam ketidaksadaran dan berbagai kelainan tingkat laku dapat disebabkan karena faktor-faktor yang terpendam dalam alam ketidaksadaran.
Sebagai dongeng yang sangat familiar di masyarakat Buton, Dongeng “Wa Ndiundiu” telah mendapat penelitian dari berbagai pihak. Pada tahun 1985, M. Arief Mattalitti melakukan penelitian yang berjudul Sastra di Buton. Dari 23 cerita yang diterbitkan, salah satunya adalah Wa Ndiundiu. Penelitian ini dimaksudkan sebagai pemetaan dan pengumpulan data saja, meskipun tetap menjelaskan beberapa unsur pembangun cerita seperti tema cerita, pelaku cerita, dan fungsi cerita.
Sumiman Udu dkk. juga telah melakukan penelitian tentang Dongeng Wa Ndiundiu tahun 2005. Penelitian tersebut menitikberatkan analisis perspektif gender. Sumiman Udu dkk menyimpulkan bahwa peran publik dilakukan oleh laki-laki, sedangkan perempuan tinggal dalam ruang domestik. Peran domestik dilakonkan oleh perempuan yang berakibat mendapat perlakuan tidak senonoh dari suami. Aspek sosial diperankan laki-laki sedangkan aspek keagamaan diarahkan untuk menyudutkan perempuan. Aspek kepemilikan dimiliki laki-laki dan pengambilan keputusan didominasi laki-laki (2005: 107—112). Akan tetapi, kedua penelitian tersebut belum menganalisis aspek kejiwaan terhadap setiap tokohnya.
Berdasarkan uriaan tersebut, penelitian ini berfokus kepada aspek kejiwaan tokoh-tokohnya. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakan struktur kepribadian, kecemasan (anxiety), dan klasifikasi emosi keempat tokoh Dongeng “Wa Ndiundiu” sebagaimana teori Psikoanalisis Sigmund Freud?
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2001:3) sebagaimana yang dikatakan oleh Bogdan dan Taylor bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sumber data penelitian ini adalah Cerita Rakyat Tradisional Wolio (Buton) yang disunting oleh Abdul Mulku Zahari tahun 1979. Penelitian kualitatif, pada hakikatnya, berusaha mengamati, melakukan interaksi, memahami, dan menafsirkan sesuatu yang menjadi fokus penelitian, dengan tujuan antara lain memperoleh pemahaman dan makna. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penulis melakukan pembacaan yang menyeluruh atas dongeng “Wa Ndiu-ndiu” untuk memahami struktur, terutama karakter tokohnya. Selanjutnya, akan diperoleh gambaran mengenai kondisi atau aspek psikologisnya yang akan menjadi wilayah yang akan dianalis menggunakan teori Psikoanalisis Sigmund Freud yaitu struktur kepribadian, kecemasan, dan klasifikasi emosi.
2. Kajian Teori
2.1.Sasra Lisan dan Dongeng
Sebagai sastra daerah, dongeng merupakan salah satu hasil kreativitas masyarakat daerah, merupakan kebudayaan daerah yang merupakan sarana ekspresi budaya (Mastuti, 2014: 97). Heddy Shri Ahimsa Putra (2006: 77) menjelaskan bahwa dongeng merupakan sebuah kisah atau cerita yang lahir dari hasil imajinasi manusia, dari khayalan manusia, walaupun unsur khayalan tersebut berasal dari apa yang ada dalam kehidupan manusia sehari-hari. Dalam khayalan ini, manusia memperoleh kebebasannya yang mutlak. Di situ bisa ditemukan hal-hal yang tidak masuk akal, yang tidak mungkin ditemui dalam kehidupan sehari-hari.
Dongeng, dalam pandangan ahli folklor, James Danandjaja (1994:83), merupakan cerita prosa rakyat yang tidak dianggap benar-benar terjadi. Selain berisikan banyak pelajaran moral atau sindiran, dongeng terutama diceritakan hanya sebagai hiburan, walaupun banyak juga yang melukiskan kebenaran, berisikan pelajaran (moral), atau bahkan sindiran. Berdasarkan uraian tersebut, istilah dongeng mencakup apa yang disebut oleh Danandjaja sebagai mite atau dongeng tentang dewa, legenda atau asal-usul, dongeng binatang, dan dongeng biasa. Oleh karena itu, membahas sastra lisan “Wa Ndiundiu” menggunakan teori Psikoanalisis Freud dalam kedudukannya sebagai dongeng menggunakan pengertiannya sebagaimana yang dikemumakan oleh Danandjaja dan Heddy Shri Ahimsa Putra.
2.2. Tokoh dan Karakter
Menurut Tarigan (1984:149) bahwa analisis mengenai motif, gambaran psikologis, uraian fisik adalah juga merupakan sarana-sarana penting dalam memperkenalkan tokoh. Lalu dijelaskannya bahwa tokoh itu adalah gerak atau character is action. Masih sekaitan dengan karakter, Sudjiman (dalam Husen (2002: 86) mengatakan bahwa tokoh (karakter) adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau perlakuan dalam berbagai peristiwa dalam cerita. Di samping tokoh utama (protagonis), ada jenis tokoh lain, yang terpenting adalah tokoh lawan (antagonis) yakni tokoh yang diciptakan untuk mengimbangi tokoh utama. Hal yang penting dan relevan dengan penelitian ini adalah bahwa konflik di antara mereka itulah yang menjadi inti dan menggerakkan cerita. Selanjutnya menurut Stanton (2007: 33) bahwa karakter merujuk pada individu-individu yang muncul dalam cerita.
Hal senada dikatakan Ibrahim (2013: 263), karakter ialah tabiat atau kebiasaan. Sementara menurut ahli psikologi, karakter adalah sebuah sistem keyakinan dan kebiasaan yang mengarahkan tindakan seorang individu. Karakter dapat dibagi dua yaitu karakter positif dan karakter negatif. Adapun Nurgiantoro (2000: 165) mengatakan bahwa character dapat berarti ‘pelaku cerita’ dan dapat pula berarti ‘perwatakan’. Antara seorang tokoh dan perwatakan yang dimilikinya, memang, merupakan suatu kepaduan utuh. Minderop (2011:98) mengatakan bahwa perwatakan adalah kualitas nalar dan perasaan para tokoh di dalam suatu karya fiksi yang dapat mencakup tidak saja tingkah laku, tabiat, atau kebiasaan, tetapi juga penampilan.
Menurut seorang pakar kepribadian, G. Ewald yang dikutip Suryabrata, watak (charakter) sebagai totalitas dari keadaan-keadaan dan cara bereaksi jiwa terhadap perangsang. Katanya, secara teoritis watak dibedakan atas dua jenis yaitu watak yang dibawa sejak lahir dan watak yang diperoleh. Watak bawaan merupakan aspek dasar daripada watak karena erat hubungannya dengan keadaan fisiologis, yaki kualitas susunan syaraf pusat. Sedangkan watak yang diperoleh yakni watak yang telah dipengaruhi oleh lingkungan, pengalaman, dan pendidikan (Suryabrata, 1988: 89).
2.3 Teori Psikoanalisis Sigmund Freud
Sigmund Freud melihat manusia dalam keadaanya yang memiliki kondisi kejiwaan yang kompleks. Freud menjelaskan bahwa ketika orang memikirkan pengalaman hidupnya yang panjang, dia mungkin berkata betapa banyak kekecewaan dan kepedihan yang dialaminya. Itu tidak akan terjadi jika saja dia berani menginterpretasikan tanda-tanda yang ada sebagai kesalahan yang diperbuatnya dan menganggap kesalahan itu sebagai pertanda kecenderungan yang melatarbelakangi tindakannya (Freud, 2009: 55).
Selanjutnya ia menjelaskan tentang kecemasan sebagai gejala kejiwaan manusia yang akan memengaruhi tindakannya. Freud membagi kecemasan ke dalam tiga jenis yaitu, kecemasan objektif, kecemasan neurotik (neurotic anxiety), dan kecemasan moral (moral anxiety). Freud kemudian menjelaskan bahwa kecemasan yang pertama menunjukkan rasa sakit yang serius, dan yang terakhir merupakan bentuk-bentuk keanehan (2009: 425). Ketiga fobia (kecemasan) ini dikelompokkannya menjadi histerya kecemasan. Tiga kecemasan tersebut sangat penting artinya dalam Psikoanalisis Freud. Hilgard (dalam Minderop, 2011: 28) menjelaskan bahwa kecemasan objektif merupakan respon atas realitas ketika seseorang merasakan bahaya dalam suatu lingkungan (menurut Freud kondisi ini sama dengan rasa takut karena ada objek yang ditakuti). Sedangkan kecemasan neurotik berasal dari konflik bawah sadar dalam diri individu, karena konflik tersebut tidak disadari orang tersebut orang tersebut tidak menyadari alasan dari kecemasan tersebut. Kecemasan moral merupakan kata lain dari rasa malu, rasa bersalah atau rasa takut mendapat sanksi. Kecemasan ini bisa muncul karena kegagalan bersikap konsisten dengan apa yang mereka yakini benar secara moral, misal tidak mampu mengurus orang tua yang memasuki usia lanjut.
Susanto (2012:57), menjelaskan bahwa Psikoanalisis Sigmund Freud memusatkan perhatiannya pada satu konsep, yakni ketidaksadaran. Sigmund Freud menyebutnya sebagai dimensi yang tidak bersuara, tersembunyi, atau pun realitas psikologis. Secara umum, ketidaksadaran itu sendiri diartikan sebagai satu rumah dari pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, tidak menyenangkan, dan emosi-emosi yang lain seperti gembira, hasrat, kecemasan, konflik atau ketegangan yang tidak terselesaikan, kesedihan, keinginan seksual, dan lain-lain.
Hal ini juga dijelaskan oleh Minderop (2011: 10—44), psikoanalisis Sigmund Freud berhubungan dengan fungsi dan perkembangan mental manusia. Meskipun pada awalnya bermula pada masalah seksual, Psikoanalisis Sigmund Freud dapat digunakan pada aspek kejiwaan yang lebih mendalam bagi manusia. Minderop kemudian menjelaskan hal-hal yang menjadi ranah Psikoanalisis Freud yaitu stuktur kepribadian, kecemasan, klasifikasi emosi, dan mekanisme pertahanan. Struktur kepribadian Freud terdiri atas id (Das Es), ego (Das Ich), dan superego (Das Ueber Ich). Adapun kecemasan (anxiety) terbagi atas tiga jenis yaitu kecemasan realistik (realistic anxiety), kecemasan neurotik (neurotic anxiety), dan kecemasan moral (moral anxiety). Klasifikasi emosi Psikoanalisis Sigmund Freud terdiri atas rasa bersalah, rasa bersalah yang dipendam, menghukum diri sendiri, rasa malu, kesedihan, kebencian, dan cinta.
Berdasarkan teori psikoanalisis Sigmund Freud analisis teks atas Dongeng “Wa Ndiundiu” yang fokus pada struktur kepribadian, kecemasan, dan klasifikasi emosi.
3. Hasil dan Pembahasan
Dongeng “Wa Ndiundiu” adalah sebuah sastra lisan yang hidup dan bertahan di tengah masyarakat Buton. Betapa tidak, “Wa Ndiundiu” menjadi dongeng pengantar tidur bagi setiap generasi sehingga kisah tersebut tidak pernah lekang oleh waktu dan terus-menerus hidup di ingatan kolektif setiap generasi. Dongeng “Wa Ndiundiu” memiliki empat karakter yaitu Ayah, Wa Ndiundiu (Ibu), La Mbatambata (anak), dan Wa Turungkoleo (kakak). Keempat karakter tersebut membentuk satu jalinan cerita beralur maju, dikisahkan secara kronologis. Pada Dongeng Wa Ndiundiu, karakter Ayah tidak memiliki nama tersendiri, tidak seperti karakter ibu yang memiliki nama yaitu Wa Ndiundiu. Selanjutnya, dua karakter lain yaitu adik dan kakak masing-masing bernama La Mbatambata (laki-laki) dan Wa Turungkoleo (perempuan).
Pada umumnya, keempat karakter di dalam Dongeng Wa Ndiundiu memiliki kedudukan signifikan di dalam cerita. Artinya, jika ada tokoh yang hilang, akan memengaruhi jalinan cerita. Meskipun dongeng tersebut tergolong pendek, akan tetapi makna yang dikandungnya cukup panjang dan dalam. Hubungan antartokoh tergolong rumit dan tidak biasa. Tidak ada karakter atau tokoh yang sekadar disebut namanya tetapi tidak hadir secara fisik di dalam cerita. Dengan demikian, keempat karakter tersebut memiliki peran, pesan, dan relasi berbeda-beda yang akan dibahas satu per satu berdasarkan teori psikoanalisis Sigmund Freud berikut ini.
3.1 Karakter Ayah
Tokoh Ayah mengalami kompleksitas kecemasan yaitu kecemasan moral (moral anxiety) disebabkan oleh perilakunya sendiri. Dorongan psikisme alam bawah sadarnya sangat dominan sehingga ia tidak memerhatikan nilai moral dan kepatutan dalam tindakannya. Di dalam Dongeng “Wa Ndiundiu”, Ayah adalah satu-satunya karakter yang tidak memiliki nama. Makna dari ketiadaan nama tersebut yaitu bahwa watak yang disandangnya jauh lebih penting dibanding hanya “sekadar” nama yang dilekatkan padanya. Atau dengan kata lain bahwa dalam konteks cerita Wa Ndiundiu, akibat yang lahir dari watak tokoh Ayah jauh lebih besar pengaruhnya bagi nasib tokoh-tokoh lainnya. Nasib tokoh-tokoh lainnya lebih banyak diakibatkan oleh akibat perilaku yang dimiliki tokoh Ayah.
Seperti apakah karakter yang tumbuh pada tokoh Ayah sehinga sedemikian rupa berakibat fatal bagi kelangsungan hidup sebuah rumah tangga? Bagaimanakah akibatnya bagi tokoh-tokoh lainnya sehingga menimbulkan tragedi besar kemanusiaan yaitu beralihnya kehidupan manusia menjadi kehidupan binatang laut? Mari kita baca kutikan awal cerita ini.
“Pada suatu hari, sebagaimana hari biasanya, ia akan pergi melaut untuk menjaring ikan. Namun, sebelum dia pergi ke laut kembali untuk memasang jaring, dia berpesan kepada istrinya agar jangan sekali-kali ada yang meminta ikan garam yang tergantung di perapian dapur”.
Kalimat “Agar jangan sekali-kali ada yang meminta ikan garam yang tergantung di perapian dapur” adalah penanda awal bahwa Ayah adalah tokoh yang pelit bagi keluarganya sendiri. Struktur kepribadian id (das es) sudah mulai berperan secara naluriah. Jika kita melihat cerita secara holistik, pesan tokoh Ayah dapat juga dimaknai sebagai ujian bagi kesetiaan istrinya. Akan tetapi, jika melihat bagian akhir cerita mengenai perilaku ayah yang menghabiskan ikan anak-anaknya yang merupakan pemberian ibunya, menjadi tanda bahwa memang tokoh Ayah adalah seorang pelit yang tidak memiliki kebaikan hati bagi keluarganya sendiri. Di sini, struktur kepribadan dalam bentuk id menjadi bagian paling dominan dalam dirinya, sehingga egonya tidak berperan ke arah positif dan juga tidak ada kearifan superego yang dapat menahan untuk melakukan perbuatan yang tidak semestinya.
Pesan Ayah terhadap istrinya secara tersirat menyimpan kecemasan objektif dan neurosis karena ada ketakutan dan kekhawatiran jika “ikan garam” tersebut diketahui keberadaan dan wujud aslinya. Kecemasan tokoh Ayah menjadi semakin terkuak ketika ia pulang memasang jaring ikan dan mendapati anaknya makan ekor ikan yang dilarangnya itu. Di sini, kecemasan objektif dan neurosis, menyatu dalam satu peristiwa dan tindakannya sekaligus. Ia cemas pada ikan garam yang ditemukan, sekaligus cemas kepada perilakunya yang menyembunyikan ikan garam itu. Akibatnya, penumpukan kecemasan itu ia wujudkan dengan cara memukul istrinya menggunakan “perkakas tenun” sampai hidung dan telinga istrinya mengeluarkan darah yang mengakibatkan pingsan.
Tokoh Ayah selaku suami dan kepala rumah tangga, juga tidak memiliki belas kasihan. Hal ini dapat diketahui saat istrinya memilih meninggalkan rumah akibat perbuatannya. Meskipun ia pada mulanya menyesal setelah melihat istrinya pingsan akibat pukulannya, akan tetapi tidak ada upaya mencari istrinya dan tidak ada reaksi untuk mengasihi anak-anaknya yang masih kecil yang ditinggalkan ibunya. Di sini, kecemasan moral (moral anxiety) akibat perbuatan kasar itu membetot dirinya, sehingga ia hanya dapat mengurung diri di rumah agar tindakannya tidak diketahui oleh orang banyak .
Kecemasan yang mendera tokoh Ayah merupakan perpaduan kecemasan dari dalam dan luar. Kecemasan dari dalam karena pelanggaran yang dilakukan istrinya sudah dapat merusak martabatnya sebagai suami. Hal ini dapat pula berdampak ke luar yaitu secara sosial dalam statusnya sebagai kepala keluarga.
Meskipun tidak dimunculkan dalam cerita, kondisi ekonomi keluarga Wa Ndiundiu dapat dikatakan tidak berkecukupan. Hal ini dapat diketahui karena pekerjaan tokoh Ayah semata melaut dan ibu hanya “tinggal di rumah saja”. Bagian lain yang memaparkan hal ini adalah ketika sang istri berubah jadi ikan duyung, mereka hanya makan ikan pemberian ibu. Dapatlah dikatakan bahwa tokoh Ayah tidak punya kreativitas lain untuk menunjang kehidupan keluarganya. Tidak memiliki pekerjaan yang berpenghasilan tetap merupakan faktor pendorong kecemasan moral (moral anxiety), sehingga ketika mendapatkan alasan untuk marah, tokoh Ayah pun langsung bereaksi dengan cara memukul istrinya hingga berdarah.
Dari segi klasifikasi emosi, tokoh Ayah memperlihatkan kemarahan yang tidak terbendung, sebagai reaksi atas pelanggaran pesannya. Kemarahan, sebagaimana yang dikatakan Krech (dalam Minderop, 2011: 39) adalah salah emosi yang paling mendasar (primary emotions). Di sisi lain, tokoh Ayah tengah memamerkan rasa kebenciannya (hate) kepada istri. Kebencian dalam klasifikasi emosi Freud bertujuan menghancurkan objek yang menjadi sasaran kebencian. Pada konteks cerita ini, yang menjadi objek adalah istri.
Kebencian (hate) tersebut dipertontonkan sang Ayah ketika anak-anaknya yang menghabiskan seluruh ikan pemberian ibunya. Wujud kebencian dalam bentuk pemukulan itu ia juga lakukan di hadapan anaknya. Secara naluriah, dalam teori Freud, tokoh Ayah menyimpan insting tanatos secara samar di bawah alam sadarnya, melalui wujud tindakan fisik dan kebencian yang dia lakukan. Ketiadaan kasih sayang, pemukulan, dan perampasan ikan kepada anaknya adalah sebuah ekspresi meledaknya “gunung es” ketidaksadarannya ke atas permukaan.
Jika kita menggunakan bahasa modern apa yang dilakukan oleh tokoh Ayah adalah termasuk kategori KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan tersebut tergolong berat karena mengakibatkan pendarahan dari telinga dan hidung istri dan mengakibatkan pingsan. Perbuatannya selain mengakibatkan rumah tangganya berantakan, juga berakibat penderitaan bagi istri dan kedua anaknya. Penderitaan tersebut tidak hanya sebatas fisik tetapi juga psikologis. Bahkan hal yang lebih fatal adalah “terkutuknya” sang istri menjadi bangsa ikan yaitu ikan duyung.
Ditinjau dari segi struktur kepribadian menurut Freud, id (das es) tokoh Ayah lebih berperan dibanding ego (das ich), dan superego (das ueber ich). Id (das es) yang hanya meminta pemenuhan lahiriah dan hawa nafsu, termanifestasikan pada tindakan pemukulan tanpa adanya kompromi. Hal ini menunjukkan bahwa ego (das ich), sang Ayah lebih condong ke wilayah negatif, sedangkan superegonya sama sekali tidak berperan. Tokoh Ayah pada dongeng “Wa Ndiundiu” adalah akumulasi karakter yang diliputi kecemasan (anxiety), pemuasan kebutuhan naluriah dan dasariah (id), kemarahan, dan kebencian yang tidak terkontrol. Hal tersebut berakibat pada kekerasan fisik yang berefek pada aspek psikis istrinya hingga berdarah, pingsan, dan meninggalkan rumah.
3.2 Karakter Wa Turungkoleo
Karakter lain yang terlibat di dalam Dongeng “Wa Ndiundiu” adalah Wa Turungkoleo. Wa Turungkoleo adalah anak pertama yang berjenis kelamin perempuan. Ia adalah tokoh yang paling dekat secara emosional dengan tokoh La Mbatambata, anak bungsu yang menjadi pemicu tragedi Wa Ndiundiu. Wa Turungkoleo boleh dikata adalah saksi atas peristiwa yang dialami tiga tokoh lainnya yaitu La Mbatambata memakan ekor ikan Ayah yang dilarang, murkanya sang Ayah, dipukulnya sang Ibu (Wa Ndiundiu), dan minggatnya ibu dari rumah menuju laut menjadi seekor ikan duyung.
Pada diri Wa Turungkoleo, bersemayam kecemasan objektif dan neurosis sebagai reaksi atas perlakukan ayahnya kepada ibunya dan dampak yang diperoleh adiknya karena kepergian ibunya. Wa Turungkoleo berada dalam pusaran kecemasan yang didapat karena adanya faktor dalam dan luar yang menakutkan. Ia cemas melihat perilaku kekerasan ayahnya terhadap ibunya. Ia juga takut melihat ibunya yang meninggalkan rumah. Pada sisi lain ia cemas melihat keadaan dan nasib yang menimpa adiknya yang masih bayi, yang masih membutuhkan air susu ibu.
Menurut Sigmund Freud (2009: 444—445), kecemasan objektif adalah reaksi terhadap persepsi bahaya eksternal terhadap suatu cedera yang diramalkan dan diketahui sebelumnya. Rekasi Wa Turungkoleo di atas sangat relevan dengan apa yang dikatakan Freud. Ia cemas kepada tindakan dan akibat dari tindakan ayahnya. Reaksi paling mungkin ia lakukan adalah dengan tidak melawan ayahnya serta membawa La Mbatambata mencari ibunya yang pergi.
Wa Turungkoleo adalah tokoh yang tidak memiliki andil terjadinya petaka di keluarganya, sehingga dapat dikatakan ia adalah korban. Meskipun demikian, ia tetap memiliki rasa kasih sayang yang dalam terhadap adiknya yang masih menyusui tetapi harus menanggung beban ditinggalkan ibunya. Ketika ibunya pergi ia pun menangis seperti kutipan berikut: “Ketika malam tiba, La Mbatambata haus ingin menyusui maka Wa Turungkoleo menangis mencari ibunya”. Pada keadaan ini, Wa Turungkoleo tengah memanifestasikan naluri hidup (eros), selain bagi dirinya, terutama bagi adiknya. Padahal, pada saat yang sama ia sementara terancam akibat naluri tanatos yang menguat dalam diri ayahnya, naluri membunuh yang destruktif.
Pada diri Wa Turungkoleo terdapat rasa kesedihan (grief) dan cinta (love) sebagai perwujudan emosi yang terdapat di dalam dirinya. Kesedihan terjadi karena ia melihat langsung ibunya dipukul oleh ayahnya. Rasa sedih itu bertambah ketika sang ibu meninggalkan rumah untuk selamanya. Rasa sedih itu semakin memuncak ketika adiknya, La Mbatambata, juga ikut kehilangan ibu dan tidak dapat menikmati air susu ibu dan kasih sayang ibu.
Menangis adalah wujud adanya rasa cinta (love) Wa Turungkoleo. Rasa cinta itu muncul karena nasib yang dialami adik kecilnya yang harus kehilangan ibu pada saat ia sangat membutuhkan kehadirannya. Selain itu, tangisan itu muncul karena rasa kehilangan ibu yang dicintainya. Di dalam kisah ini, tidak ada bagian yang menunjukkan rasa cinta atau benci kepada Ayah oleh Wa Turungkoleo. Hal ini sebetulnya menunjukkan bahwa rasa cinta kepada adik dan ibunya, serta rasa kehilangannya atas kepergian ibunya mengalahkan rasa benci kepada ayahnya.
Bagian yang paling menunjukkan rasa cinta Wa Turungkoleo yang sesungguhnya adalah ketika ia berupaya mencari ibunya yang telah pergi meninggalkan rumah. Sambil mencari jejak ibunya, ia menggendong La Mbatambata sambil bernyanyi yang sangat menggugah hati. Respon yang dilakukan oleh Wa Turungkoleo tersebut dalam struktur kepribadian Freud berada pada tahap ego (das ich) yang merupakan aspek psikologis yang timbul karena kebutuhan organisme untuk berhubungan baik dengan dunia kenyataan. Hal yang menarik adalah selain karena ingin bertemu ibunya, respon psikologis Wa Turungkoleo tersebut dimaksudkan agar La Mbatambata dapat bertemu dan menyusui kepada ibunya. Respon tersebut oleh Suryabrata (1988: 147) disebut proses sekunder yaitu proses berpikir realistis merumuskan suatu rencana untuk pemuasan kebutuhan dan mengujinya dengan suatu tindakan, apakah rencana tersebut berhasil atau tidak. Terkait dengan dongeng ini, usaha yang dilakukan Wa Ndiundiu untuk bertemu dengan ibunya dan agar La Mbatambata dapat menyusui, berhasil.
Wa Turungkoleo sebetulnya menaruh rasa sakit hati kepada adiknya, “andai kemarin engkau tidak makan ikan garam bapak, maka tidak akan seperti ini”. Akan tetapi, itu hanya sebatas ucapan saja. Ia tahu bahwa adiknya yang masih kecil, tidak tahu-menahu hal yang dilarang oleh ayahnya. Di sini, Wa Turungkoleo menunjukkan sifat sabar yang besar yaitu menggendong adiknya (wujud tanggung jawab) menuju ibunya yang jauh di tepi pantai. Ia memikul rasa tanggung itu agar adiknya yang masih balita dapat menyusui ibunya yang tidak lama lagi berubah menjadi ikan duyung. Wa Turungkoleo tahu bahwa meskipun masalah yang mendera keluarganya sangat rumit dan besar (ibunya menjadi ikan), tetapi proses menyusui sebagai hak dan kewajiban (La Mbatambata dan ibunya) tetap berjalan. Wa Turungkoleo adalah karakter yang mengemban sisi moral pada dongeng ini. Pada keadaan ini, Wa Turungkoleo tidak hanya mampu memperlihatkan ego (das ich) yang positif, tetapi sekaligus memberikan kearifan super ego (das ueber ich) yang matang.
Wa Turungkoleo memiliki naluri atau insting yang baik bagi kelangsungan hidup keluarganya. Menurt Freud, naluri itu terbagi dua yaitu eros atau naluri kehidupan (life instinct) dan nalur kematian (destructive instinct). Pada diri Wa Turungkoleo ia memiliki naluri kehidupan yaitu eros bagi keluarganya, khususnya bagi adiknya, La Mbatambata. Hal itu ia tunjukkan dengan cara mencari ibunya ke pantai agar adiknya tetap dapat menyusui untuk kelangsungan pertumbuhan badannya. Agar ia dapat bertahan hidup. Wa Turungkoleo memiliki sifat baik untuk keluarganya seperti tampak dalam kutipan berikut:
Tidak lama berjalan ia menemukan sobekan baju ibunya dan berkata lagi kepada adiknya, “Ibu kita telah telanjang tidak ada sehelai kain pun yang meliliti tubuhnya karena baju yang dikenakan habis dirobek-robek.” Tidak lama kemudian mereka sampai ke tepi pantai berhadapan dengan tempat ibunya menyelam kemarin. Di atas batu, Wa Turungkoleo melihat jimat milik ibunya dan menyimpan sebagai tanda mata dari ibunya.
Meskipun ibunya meninggalkan ia dan adiknya, Wa Turungkoleo tetap memiliki rasa belas kasih kepada ibunya yang rela telanjang demi meninggalkan jejaknya kepada dua anaknya dengan cara menyobek-nyobek kain bajunya sepanjang jalan. Pada tahap ini, Wa Turungkoleo tidak menghardik adiknya dan sebaliknya tidak mengutuk ibunya. Sepertinya, meskipun tidak ia katakan secara langsung, ia menimpakan kesalahan itu kepada ayahnya yang memiliki sifat tanatos, membunuh.
Di sisi lain, meskipun Wa Turungkoleo memiliki rasa rindu yang besar kepada ibunya, tetapi dalam nyanyian yang dilantunkannya ia memanggil ibunya untuk menyusui adiknya, La Mbatambata. Ia rela memendam rasa rindunya itu dengan mengutamakan nasib adiknya yang masih kecil, menyusui, dan tergantung kepada ibunya. Pada posisi ini, Wa Turungkoleo tidak ingin menjadi bagian yang justru memperumit masalah yang terjadi di dalam keluarganya. Ia tidak melawan bapaknya yang penuh amarah memukul ibunya. Ia tidak menghardik adiknya yang telah memakan ikan terlarang ayahnya. Ia juga tidak dendam terhadap ibunya yang “tega” meninggalkan rumah menuju rumah yang lain yaitu laut.
Di tengah kemelut yang melanda keluarganya, Wa Turungkoleo memperlihatkan jiwa yang matang dengan tetap menjaga rahasia dan kejujuran sebagai wujud cinta. Hal ini dibuktikan dengan tidak memberitahukan kepada ayahnya bahwa ikan yang ia bawa adalah pemberian ibunya. Kutipan berikut ini mempertegas hal itu “Wa Turungkoleo mengingat pesan ibunya, bahwa jangan sekali-kali bilang bahwa ikan itu pemberian ibunya tetapi diberikan oleh orang yang merasa kasihan. Jika bapak bertanya apakah kalian bertemu ibu kalian, jawab tidak”. Hal tersebut ia lakukan, selain sebagai sifat kejujuran, juga ia tidak ingin ayahnya tahu bahwa ibunya tinggal di laut. Ia tidak ingin ayahnya tahu bahwa ia dan La Mbatambata bertemu ibunya di tepi laut. Sebab jika ayahnya tahu, boleh saja ia ikut menemui ibunya. Jika hal tersebut terjadi, segala hal yang tidak diinginkan dapat saja terjadi.
Di balik kejujuran dan kesabaran tersebut, terdapat rasa takut kepada ayahnya yang dapat berbuat brutal kapan saja. Wa Turungkoleo benar-benar tidak ingin menimbulkan masalah dalam keadaan ditinggal ibunya. Saat ayahnya menghabiskan seluruh ikan pemberian ibunya, ia tidak melakukan perlawanan saat tulang-belulang ikan diberikan untuk dia dan adiknya. Masa depan adiknya jauh lebih penting dibanding melakukan perlawanan terhadap ayahnya.
Sampai dongeng tersebut berakhir, tokoh Ayah tidak pernah mengetahui bahwa istrinya telah berubah menjadi Wa Ndiundiu atau ikan duyung. Meskipun La Mbatambata menyaksikan ibunya di laut bahkan sempat dua kali menyusui di pasir tepi pantai, tetapi ia tidak benar-benar mengerti apa yang terjadi, karena usianya yang masih balita. Sebaliknya, meskipun bukan tokoh utama, Wa Turungkoleo menjadi saksi utama kejadian yang dialami ibunya. Akan tetapi, demi menjaga rahasia ibunya, ia tidak menceritakan persoalan tersebut kepada ayahnya. Baginya, Ayahnya adalah bagian dari masalah, bukan solusi! Kesabaran Wa Turungkoleo untuk mempertemukan ibu dan adiknya tidak pernah reda. Bahkan saat detik-detik perubahan ibunya menjadi ikan duyung ia pun masih sempat ke tepi pantai untuk mencari ibunya, meskipun tidak ketemu.
Meskipun belum berusia dewasa, Wa Turungkoleo memperlihatkan adanya kecemasan objektif dan neurosis dalam dirinya. Akan tetapi, ia juga memperlihatkan keseimbangan ego yang matang, menunjukkan superego yang begitu arif, jiwa eros yang kuat. Ia rela menggendong adiknya, tidak melakukan perlawanan kepada ayahnya, tidak memarahi adiknya, dan ia pun mencari ibunya ke pantai demi adiknya agar tetap dapat menyusui. Cinta (love) sebagai tingkat klasifikasi emosi tertinggi, ia persembahkan bagi keluarganya.
3.3 Karakter La Mbatambata
Struktur kepribadian manusia dalam teori psikoanalisis terdiri dari id, ego, dan superego. Id adalah struktur paling mendasar atau bersifat dasariah dari kepribadian. Ia bekerja dalam keadaan tidak disadari menurut prinsip kesenangan yang bertujuan pemenuhan kepuasan yang segera. Untuk dapat memosisikan struktur kepribadian La Mbatambata dalam Dongeng “Wa Ndiundiu”, ada baiknya penulis menggambarkan siatuasi keluarga ketika masih aman.
Pada mulanya, kehidupan keluarga La Mbatambata berjalan normal sebagaimana biasa. Ayahnya pergi memasang jaring ikan setiap pagi, ibunya memasak, dan La Mbatambata serta Wa Turungkoleo bermain di rumah. Akan tetapi, masalah muncul ketika La Mbatambata menangis minta makan ikan yang digarami ayahnya di perapian. Ibunya yang telah diamanati untuk tidak boleh ada yang meminta ikan garam tersebut, akhirnya melanggar pesan suaminya. Tangisan La Mbatambata yang membanting-banting dirinya di lantai membuat ibunya melanggar amanat.
Berdasarkan kutipan tersebut dipat dikatakan tragedi yang menimpa keluarga Wa Turungkoleo bermula dari La Mbtambata. Akan tetapi, karena ia adalah sosok yang masih balita, sehingga kesalahan tidak dapat ditimpakan kepadanya. Ia tidak pernah tahu bahwa ayahnya melarang ibunya siapa pun yang meminta ikan garam itu, tidak boleh diberikan. Jelaslah bahwa, La Mbatambata yang masih berusia balita itu lebih didominasi struktur kepribadian id. Dorongan ingin makan merupakan rangsangan paling primitif dan dasariah yang harus dipenuhi tanpa terhalang oleh nilai dan sistem tertentu.
Kondisi La Mbatambata yang masih kecil, mengharuskan ia untuk meminta terpenuhi kebutuhannya. Keadaan ini disebut sebagai tak sadar yaitu bagian yang paling dalam dari struktur kesadaran dan menurut Freud, merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Secara khusus Freud membuktikan bahwa ketidaksadaran itu berisi insting dan impuls yang dibawa dari lahir, dan pengalaman-pengalaman traumatik (biasanya pada masa anak-anak) yang ditekan oleh kesadaran dipindah ke daerah tak sadar. Pada tahap perkembangan kepribadian menurut Freud sebagaimana yang dikutip Agustina (2014: 12), La Mbatambata berada pada fase infantile (0,0-5,0 tahun). Fase ini dibedakan menjadi tiga yaitu fase oral (0-1 tahun), fase anal (1-3 tahun), dan fase falik (3-5 tahun). Pada dongeng Wa Ndiundiu tidak ada uraian mengenai usia La Mbatambata, tetapi dari perilakunya dapat dipastikan bahwa ia lebih dekat kepada fase pertama, karena kebergantungannya terhadap air susu ibu.
Fase infantile La Mbatambata tersebut relevan dengan kepribadian id (das es) pada dirinya yang masih didominasi hal-hal yang dibawa sejak lahir (unsur biologis), termasuk insting-insting. Jadi yang pedoman menjadi pedoman dalam berfungsinya id (da es) ialah menghindarakan diri dari ketidakenakan dan mengejar keenakan. Pedoman ini disebut Freud sebagai prinsif kenikmatan atau prinsif keenakan ‘Lust prinzip, the pleasure principle’ (Suryabrata, 1988: 146). Jadi, rengekan dan tangisan La Mbatambata sampai membanting diri di lantai adalah bagian dari usaha pemenuhan prinsif kenikmatan itu.
Sejalan dengan pendapat Agustina, Desyandri (2014) menjelaskan bahwa struktur kepribadian La Mbatambata tersebut beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan (pleasure principle), yaitu: berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Bagi kepribadian id (das es), kenikmatan adalah keadaan yang relatif inaktif atau tingkat energi yang rendah, dan rasa sakit adalah tegangan atau peningkatan energi yang mendambakan kepuasan. La Mbatambata tidak menginginkan rasa lapar pada dirinya, sehingga meronta-ronta menangis dan tidak ingin ada rasa sakit.
Masih dijelaskan Desyandri (2014) bahwa ketika ada stimulus yang memicu energi untuk bekerja–timbul tegangan energi–-id beroperasi dengan prinsip kenikmatan, berusaha mengurangi atau menghilangkan tegangan itu. Pleasure principle diproses dengan dua cara, tindak refleks (reflex actions) dan proses primer (primary process). Tindak refleks adalah reaksi otomatis yang dibawa sejak lahir seperti mengejapkan mata – dipakai untuk menangani pemuasan rangsang sederhana dan biasanya segera dapat dilakukan. Proses primer adalah reaksi membayangkan/mengkhayal sesuatu yang dapat mengurangi atau menghilangkan tegangan–dipakai untuk menangani stimulus kompleks, seperti bayi yang lapar membayangkan makanan atau puting ibunya. Proses membentuk gambaran objek yang dapat mengurangi tegangan, disebut pemenuhan hasrat (nosh fullment), misalnya mimpi, lamunan, dan halusinasi psikotik. Pada kondisi inilah, yang menyebabkan La Mbatambata menangis karena ingin makan ikan garam yang terlarang itu.
Jika dimaknai bahwa La Mbatambata tidak mengetahui kalau ikan garam itu dilarang ayahnya untuk memakannya, maka pesan yang dapat ditarik dari kejadian tersebut sangat sederhana, yaitu anak kecil tidak tahu masalah. Akan tetapi banyak tafsir yang dapat hadir dari rontaan La Mbatambata sebagai anak kecil untuk minta ikan garam yang ternyata adalah seekor tikus yang dibelah lalu digarami ayahnya. Pertanyaannya, mengapa La Mbatambata tidak menerima saran ibunya untuk memakan ikan mas saja yang jauh lebih lezat dan bergizi?
Dari segi psikologis, La Mbatambata adalah simbol kepolosan dan kejujuran. Sehingga, secara semiotik, ia mengungkap sebuah kenyataan kenyataan di dalam keluarganya. Pertanyaan yang relevan dengan konteks ini adalah mengapa tidak ada reaksi ibu dan La Mbatambata terhadap keberadaan tikus yang dianggap sebagai seekor ikan? Bukankah selayaknya manusia tidak pantas memakan seekor tikus? Hal yang menarik dan sekaligus pertanyaan dari dongeng “Wa Ndiundiu” adalah tidak ada dialog atau narasi selanjutnya tentang seekor tikus yang digarami sang ayah tersebut. Seakan-akan secara sepintas, ia bukanlah persoalan yang pantas diungkit di jalinan cerita selanjutnya.
Terkait dengan “tikus” tersebut, ternyata ia bukanlah sebuah makna simbolik bahwa watak ayahnya seperti tikus, tetapi pada kurun waktu tertentu pada masyarakat Buton di masa silam, sering terjadi paceklik dan kelaparan berkepanjanga sehingga tikus pun dijadikan sebagai lauk pengganti ikan (Asrif, 2015). Itulah sebabnya, di dalam keluarga La Mbatambata, tidak reaksi khusus atas kehadiran tikus dan tidak ada kelanjutan cerita yang membahas tikus tersebut.
Struktur kepribadian id (das es) hanya mampu membayangkan sesuatu, tanpa mampu membedakan khayalan itu dengan kenyataan yang benar-benar memuaskan kebutuhan. Id tidak mampu menilai atau membedakan benar-salah, tidak tabu, dan moral. Dengan demikian, kepolosan seorang La Mbatambata yang meminta ikan garam untuk ia makan sehingga membuka watak ayahnya yang sesungguhnya yaitu pemarah, pendendam, pemalas, dan telah menggarami tikus untuk dimakan seperti ikan. Kepolosan yang natural tersebut adalah wujud dari naluri alam bawah sadar La Mbatambata yang nirmoral. Meskipun demikian, dapat dijelaskan bahwa tikus dalam keluarga La Mbatambata adalah sebuah tanda kelaparan dan kemiskinan, sehingga menjadi salah satu pemicu konflik psikologis yang mendera, baik bagi tokoh Ayah maupun bagi tokoh ibu atau Wa Ndiundiu.
Pada konteks dongeng “Wa Ndiundiu”, karakter La Mbatambata dihadirkan untuk menyeimbangkan peran tokoh orang dewasa dan tokoh kepolosan. Tokoh dewasa (ayah dan ibu) identik dengan berbagai masalah, sedangkan tokoh anak-anak yang polos (La Mbatambata) meskipun ia yang memantik permasalahan yang tidak disengaja, ia hadir justru menelenjangi pokok persoalan yang sebenarnya, baik yang dialami ayahnya maupun ibunya.
La Mbatambata, meskipun adalah pihak pemantik persoalan, tetapi ia memberi pesan kuat bahwa sebesar apa pun masalah yang dihadapi kedua orang tuanya, akan tetapi sebagai balita ia tetap harus mendapatkan haknya yang paling azazi yaitu air susu ibu. Itulah sebabnya, meskipun ibunya memilih tinggal di laut sebagai ikan duyung, ia tetap bersusah payah ke sana untuk menyusui bersama Wa Turungkoleo yang menggendongnya. Hal yang paling menyentuh adalah ketika dalam proses perubahan dari manusia menjadi ikan duyung, ibunya tetap setia menyusui La Mbatambata, agar keberlangsungna kehidupan anaknya (umat manusia) tetap terjaga.
Menurut Freud, alam bawah sadar merupakan kunci memahami perilaku seseorang (Minderop, 2011: 13). Dalam hubungannya dengan Wa Ndiundiu, tokoh La Mbatambata masih dikuasai oleh alam bawah sadar dan struktur kepribadian dalam fase id (das es). Ia merupakan tempat dari dorongan-dorongan primitif, yaitu dorongan-dorongan yang belum dibentuk atau dipengaruhi oleh kebudayaan yaitu dorongan untuk hidup dan mempertahankan kehidupan (life instinct) dan dorongan untuk mati (death instinct).
3.4 Karakter Wa Ndiundiu (Ibu)
Dongeng “Wa Ndiundiu” terkenal salah satunya disebabkan karena judulnya adalah nama karakter utamanya yaitu Wa Ndiundiu. Wa Ndiundiu dalam bahasa-bahasa di Buton berarti ikan duyung. Mengapa dongeng ini menggunakan nama tokohnya sebagai judulnya? Jawaban yang paling mungkin adalah karena Wa Ndiudiu merupakan tokoh yang dapat merepresentasikan tema dan amanat cerita. Tokoh Wa Ndiudiu adalah sosok yang paling menanggung derita besar yaitu berubah wujud dari manusia menjadi ikan duyung.
Mengapa tokoh ibu dapat dengan mudah berubah wujud jadi ikan duyung? Mari kita baca kutipan berikut ini:
Pada suatu hari, sebagaimana hari biasanya, ia akan pergi melaut untuk menjaring ikan. Namun, sebelum dia pergi ke laut kembali untuk memasang jaring, dia berpesan kepada istrinya agar jangan sekali-kali ada yang meminta ikan garam yang tergantung di perapian dapur. Istrinya menyahuti, bahwa siapa lagi yang berani meminta dan mengambil ikan itu kalau bukan anak-anak ini. Sang suami menjawab, sekali pun mereka, jangan berikan, demikian pesan suaminya sambil mengambil pukatnya lalu pergi ke laut. Belum lama setelah bapaknya pergi, anak kecilnya La Mbata-mbata menangis ingin makan ikan garam milik bapaknya. Tidak ingin melanggar pesan suaminya, ibunya memberikan ikan mas tapi anak itu tidak mau. Maunya makan ikan milik bapaknya. Dia menangis tidak berhenti dan membanting-mbanting dirinya. Ibunya merasa kasiahan melihat La Mbatambata, karena itu ia pergi ke dapur untuk memotong ikan bagian ekornya lalu dibakarkan untuk anaknya. Karena tangisan anakanya itu maka si ibu pun lupa pesan suaminya.
Kutipan paragraf tersebut menjelaskan bahwa sebetulnya tidak ada masalah besar yang terjadi di dalam keluarga Wa Ndiundiu. Suaminya pergi bekerja di laut yaitu memasang jaring untuk mendapatkan ikan. Sebelum berangkat ia berpesan kepada Wa Ndiundiu agar tidak boleh ada yang meminta ikan garam—yang sebetulnya adalah tikus digarami—yang tergantung di perapian dapur. Awal petaka datang ketika La Mbatambata meronta-ronta minta ikan garam yang terlarang itu. Karena tidak tega melihat anak bungsunya yang masih balita itu mengguling-gulinggkan dirinya ke lantai, ia pun memotong bagian ekor ikan lalu dibakar untuk sang anak. Ia lupa pesan suami. Tidak tega adalah wujud kesadaran ego (das ich) yang positif seorang ibu, meskipun berkibat fatal baginya nanti.
Tidak lama kemudian, suaminya datang dan marah besar karena ikan garam yang dilarang untuk dimakan itu telah disantap oleh anaknya. Merasa pesannya tidak dihiraukan, ia pun memukul istrinya menggunakan perkakas tenun sampai telinga dan hidung istrinya mengeluarkan darah. Di sini, kecemasan objektif (objektif neurosis) melanda diri Wa Ndiundiu. Hal itu dapat ketahui melalui reaksi yang dilakukannya yaitu tidak melawan dan pergid ari rumah. Menurut Sigmund Freud, kecemasan objektif adalah ketakutan riil terkait dengan reflkes gerakan dan dianggap sebagai suatu wujud dari insting perlindungan diri. Kemunculannya, yaitu objek-objek dan situasi-situasi di mana kecemasan dirasakan akan sangat bergantung kepada seberapa besar pengetahuan dan rasa berkuasa seseorang berkaitan dengan dunia luar (2009:445). Penjelasan mengenai hal ini akan penulis uraikan selanjutnya.
Pertanyaan yang muncul adalah mengapa Wa Ndiundiu tidak melakukan perlawanan atau setidaknya pembelaan? Tidak ada teks yang menunjukkan hal itu terjadi. Di sini, pemaknaan dapat dikatakan bahwa ketiadaan pembelaan apalagi perlawanan sang istri disebabkan oleh perasaan bersalah karena telah melanggar pesan suami. Rasa bersalah dalam teori Freud disebabkan oleh adanya konflik antara ekspresi impuls dan standar moral (impuls expression versus moral standrads). Rasa bersalah itu hadir karena ia berposisi sebagai istri sehingga ia tidak mungkin melakukan perlawanan. Artinya, budaya patriarki telah mengakar begitu kuat di rumah tangganya, yang sangat mungkin merupakan cerminan sosial di lingkungannya. Ada stereotype selaku istri di dalam keluarga. Akan tetapi, reaksi yang muncul dari dalam diri karakter Wa Ndiundiu sungguh di luar dugaan, yaitu meninggalkan rumah dengan alasan yang sangat menyentuh, seperti kutipan di bawah ini:
Tidak lama kemudian sang ibu sadar dan memanggil anak-anaknya dia berkata “Saya akan meningggalkan kalian karena bapak kalian lebih menyayangi ikannya dibandingkan kalian anak-anakanya.
Alasan keperigian Wa Ndiundiu dari rumah bukan karena ia telah disakiti oleh suaminya sebagai korban dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tetapi karena “Bapak kalian lebih menyayangi ikannya dibandingkan kalian anak-anakanya”. Alasan ini adalah sebuah tanda betapa besar rasa sayangnya Wa Ndiundiu sebagai ibu kepada anak-anaknya. Meskipun ia sendiri yang menjadi korban kekerasan suaminya tetapi ia telah melampaui rasa sayang hanya kepada dirinya. Cinta kepada anaknya mengalahkan derita yang menderanya. Cinta (love) dalam klasifikasi emosi Freudian, berada pada tingkatan tertinggi. Ia merasa ada pengkhianatan besar dari suaminya sebagai bapak dari anak-anaknya yang lebih mementingkan ikan garam daripada rasa lapar dan rasa sayang kepada anaknya.
Terkait dengan hal ini, sebagaimana yang dikatakan Freud di atas mengenai kecemasan objektif bahwa kemunculannya yaitu objek-objek dan situasi-situasi di mana kecemasan dirasakan akan sangat bergantung kepada seberapa besar pengetahuan dan rasa berkuasa seseorang berkaitan dengan dunia luar. Kekuasaan Wa Ndiundiu terkait dengan dunia luar sangat lemah, sehingga hal yang dapat ia lakukan adalah dengan cara menenggelamkan diri ke laut, yang kemudian membuatnya berubah jadi ikan duyung. Objek dan situasi yang ia rasakan adalah kekasaran sang suami dan tekanan batin yang mendalam akibat kesalahan yang ia lakukan. Pada situasi ini, kecemasan neurotik juga hadir sekaligus. Akibat pemenuhan instingnya sendiri—dengan cara mengambil ika garam terlrang itu—ia dilanda kecemasan psikologis yaitu merasa akan mendapatkan hukuman akibat perbuatannya. Hukuman tersebut pada akhirnya menjadi kenyataan.
Selain itu, alasan Wa Ndiundiu bahwa suaminya lebih sayang ikan dibanding kepada anaknya adalah wujud dari pertimbangannya bahwa ia memang mengakui adanya pelanggaran terhadap standar moral. Standar moral tersebut adalah melanggar petuah suami. Rasa bersalah tersebut diperparah oleh perilaku neurotik yakni ketika individu tidak mampu mengatasi problem hidup seraya menghindarinya melalui manuver defensif yang mengakibatkan rasa bersalah dan tidak bahagia. Ia gagal berhubungan langsung dengan kondisi tertentu, dalam hal ini gagal meyakinkan suaminya (Minderop, 2011: 40).
Dari struktur kepribadian, Wa Ndiundiu berada pada tingkatn ego dan superego. Setelah lama ia mempertimbangkan, apakah ia akan menuruti keinginan insting lapar anaknya yang didominasi oleh ia, ia akhirnya mengikuti keinginan anaknya itu. Ia berada dalam situasi sulit, antara mengikuti permintaan naluriah anaknya atau mendapat ancaman ego negatif dari suaminya. Akan tetapi, pada saat suaminya marah dan berlaku kasar, ia berhasil menahan diri untuk tidak melawan kekerasan suaminya tersebut. Ia juga tidak memarahi dan menyakiti anak kecilnya yang meminta ikan garam yang mengakibatkan lahirnya siksaan dari suaminya.
Disebabkan oleh rasa sayang kepada ikan melebihi rasa sayangnya kepada anaknya yang mengakibatkan Wa Ndiudiu mengalamai kekerasan fisik dan fsikis, Wa Ndiundiu memilih meninggalkan rumah. Sebenarnya, rasa sakit yang ia alami adalah representasi kesakitan lain yang dialami oleh anaknya yang dilarang memakan ikan garam oleh ayahnya. Artinya, derita Wa Ndiundiu adalah derita anaknya juga. Wa Ndiundiu mengalami derita fisik yaitu pemukulan yang mengakibatkan pendarahan di hidung dan telinga. Ia juga mengalami derita fsikis yaitu guncangan batin karena sang suami tega melakukan kekerasan terhadap dirinya. Guncangan fsikis yang lain adalah karena suamianya lebih sayang kepada ikan garam dibanding kepada anaknya. Kecemasan (anxiety) dalam dirinya sudah begitu kompleks.
Di tengah belitan derita yang mendera, cinta Wa Ndiundiu kepada kedua anaknya tidak pernah luntur, meskipun awal mula kejadian tersebut disebabkan oleh keinginan La Mbatambata untuk makan ikan garam yang dlarang bapaknya itu. Akan tetapi, Wa Ndiundiu tidak menimpakan kesalahan tersebut karena ia tahu, La Mbatambata masih kecil, belum mengerti salah dan tidak salah. Rasa cinta muncul dapat ditelusri melalui kutian berikut:
Dia mengelus-elus kedua naknya tersebut dan disusuinya La Mbatambata sampai kenyang. Dicium dan dipeluknya anaknya sepuas-puasnya. Lalu berkatalah dia kepada anaknya yang tua “Sayangilah adikmu, jaga, dan pelihara dia dengan baik! Berkata pula dia kepada La Mbata-mbta, andai engkau La Mbata-mbata tidak ingin makan ikan garam bapakmu tidaklah aku menderita seperti ini. Setelah kenyang disusui, La mbatambata tidur di tempat tidunya, lalu ibu itu mengambil baju dan sarungnya. Ia pun memberi tahu anaknya bahwa dia akan pergi.
Wa Ndiundiu mengerti bahwa dalam keadaan apa pun, anaknya harus mendapatkan haknya yaitu air susu ibu yang menjadi kewajiban baginya. Bahkan dalam situasi batin yang tertekan dan tidak menentu, ia menyusui La Mbatambata sampai kekenyangan. Di tengah kekalutan yang besar, ia berpesan kepada Wa Turungkoleo, “Sayangilah adikmu, jaga, dan pelihara dia dengan baik”! Ada perasaan tidak tega meninggalkan anaknya yang masih menyusui, tetapi ia harus pergi karena ia tidak kuasa menanggung luka lebih besar besar jika ia tetap bertahan di rumah yaitu penderitaan lahir batin akibat kekerasan fisik dan psikis dari suaminya.
Sempat pula Wa Ndiundiu mengatakan kepada anaknya yang masih bayi itu bahwa “Andai engkau La Mbata-mbata tidak ingin makan ikan garam bapakmu tidaklah aku menderita seperti ini”. Rasa kesal kepada La Mbatambata tidak diutarakan secara prontal oleh ibunya, karena ia tahu bahwa sesungguhnya dialah yang melanggar pesan suaminya. Ia pun tahu bahwa “kekerasan hati” La Mbatambata untuk meminta ikan garam tersebut adalah karena usianya yang masih kecil yang belum mengerti larangan. Akan tetapi, hal yang tidak ia duga adalah justru reaksi suaminya yang di luar dugaan: memukulnya hingga berdarah dan pingsan!
Dari klasifikasi emosionalitas, Wa Ndiundiu mengalami tiga kecemasan sekaligus. Kecemasan realistik (realistic anxiety) muncul akibat takut kepada bahaya yang nyata ada di dunia luar. Bahaya yang nyata itu adalah tindakan kekerasan suaminya. Kecemasan ini menjadi asal muasal timbulnya kecemasan neurotik dan kecemasan moral. Pada kecemasan neurotik (neurotic anxiety) Wa Ndiundiu cemas dan takut terhadap hukuman yang bakal diterima dari suami akibat ia memuaskan insting dengan caranya sendiri, yang diyakininya bakal menuai hukuman. Insting yang dimaksud adalah pemenuhan keinginan anaknya yang meminta ikan garam akibat kelaparan. Hukuman itu memang nyata adanya yaitu pemukulan secara fisik. Sementara kecemasan moral (moral anxiety) timbul karena Wa Ndiundiu melanggar standar nilai keluarga yaitu pesan suaminya agar tidak memakan ikan garam.
Wa Ndiundiu adalah sosok ibu yang sangat mencintai anak-anaknya. Cinta adalah bentuk perwujudan emosi paling tinggi dalam teori Freud. Wa Ndiundiu rela telanjang demi meninggalkan jejak dirinya kepada kedua anaknya. Saat meninggalkan rumah, ia merobek-robek sarung dan bajunya lalu dijatuhkan sepanjang jalan agar anak-anaknya mudah menemukannya bila anak-ananya mencarinya besok lusa. Tidak hanya baju yang ia robek-robek, sesampainya di pantai dia membuka jimat yang melilit di pinggangnya dan diletakkan di atas batu di pinggir pantai.
Apa yang dilakukan oleh Wa Ndiundiu adalah sebentuk pengorbanan eksistensial dalam merespon penderitaan yang ia alami dari suaminya sendiri. Bahkan, sebagaimana yang dikatakan oleh Wa Turungkoleo, “Ibu kita telah telanjang tidak ada sehelai kain pun yang meliliti tubuhnya karena baju yang dikenakan habis dirobek-robek”. Ia rela menanggalkan seluruh pakaian yang menutup tubuhnya, agar ia tidak hilang begitu saja dari pencarian anak-anaknya, dan tidak raib begitu saja dari sejarah kemanusiaan. Dengan demikian, Wa Ndiundiu telah sampai kepada “ketelanjangan” spiritual dan filosofis yang paling sublim.
Perasaan cinta bervariasi dalam beberapa bentuk. Intensitas pengalaman pun memiliki rentang dari yang terlembut sampai yang amat mendalam. Derajat tensi dari rasa sayang yang paling sublim sampai kepada gelora nafsu yang kasar dan agitatif. Cinta diikuti perasaan setia dan sayang. Cinta tidak mementingkan diri sendiri, sebagai cinta sejati (Minderop, 2011: 45). Dalam konteks cerita ini, Wa Ndiundiu telah mewujudkan cintanya kepada anaknya, meskipun ia harus menjadi korban.
Pada hari terakhir pertemuan dengan kedua anaknya, Wa Ndiundiu menyusui La Mbatambata dengan penuh cinta sampai kekenyangan. Hari itu adalah terakhir kalinya mereka bertemu. Wa Ndiundiu segera menjadi ikan, seluruh tubuhnya ditumbuhi sisik sehingga tidak mungkin lagi naik ke darat. Derita yang ia alami telah paripurna. Cinta yang ia berikan kepada anaknya sudah sempurna. Akan tetapi, sesungguhnya Wa Ndiundiu adalah wujud sosok yang dalam dirinya terhimpun berbagai gejala kejiwaan sekaligus. Kepergiannya ke laut adalah akibat dari rasa bersalah yang dipendam. Dalam kasus rasa bersalah yang dipendam, seseorang dapat bersikap baik, tetapi dapat juga buruk. Pada kasus Wa Ndiundiu ia memperlihatkan sikap baik kepada La Mbatambata dengan cara menyusuinya, dan memberi ikan kepada kedua anaknya untuk dibawa pulang. Akan tetapi, di sisi lain, keputusannya ke laut berakibat tidak baik baginya, yaitu berubah wujud jadi ikan.
Selain itu, Wa Ndiundiu juga berada pada keadaan menghukum diri sendiri (self punshing). Hukuman pada diri sendiri yaitu ia mengubah diri dari manusia ke ikan, selamanya. Sebuah hukuman yang fatalistis. Eros dan tanatos hadir sekaligus dalam reaksi hidupnya. Eros, karena ia masih menyusui anaknya dan memikirkan keluarganya dan tanatos karena ia mengakhiri hidupnya sebagai manusia menjadi ikan. Ia juga terbelenggu rasa malu dan sedih (grief) karena dipukul oleh suami di hadapan anaknya. Rasa malu juga diakibatkan oleh kelakuannya melanggar pesan suaminya. Beragam kondisi emosional ini serta deraan kecemasan yang tidak dapat ia hindari’’, membawa Wa Ndiundiu kepada keputusan yaitu meninggalkan rumah, pergi ke laut, dan mengubah diri menjadi ikan duyung.
4. Simpulan
Berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik beberapa simpulan berikut. Ditinjau dari segi struktur kepribadian menurut Freud, id tokoh Ayah lebih berperan tinimban ego, dan superego. Id yang hanya meminta pemenuhan lahiriah dan hawa nafsu, termanifestasikan pada tindakan pemukulan. Hal ini ini menunjukkan bahwa ego sang Ayah lebih condong ke wilayah negatif, sedangkan superego-nya sama sekali tidak berperan. Tokoh Ayah pada dongeng “Wa Ndiundiu” adalah akumulasi karkater yang diliputi kecemasan (anxiety), pemuasan kebutuhan naluriah dan dasariah (id), kemarahan, dan kebencian yang tidak terkontrol, berakibat pada kekerasan fisik berakibat psikis kepada istrinya hingga berdarah pingsan, dan meninggalkan rumah. Tokoh Ayah adalah akumulasi karkater yang diliputi kecemasan (anxiety), pemuasan kebutuhan naluriah dan dasariah (id), kemarahan, dan kebencian yang tidak terkontrol.
Tokoh Wa Turungkoleo memiliki rasa kesedihan, cinta dan eros. Kecemasan juga mengemuka dalam dirinya akan tetapi ia dengan baik mampu mengendalikan diri dan keluarganya karena ia memiliki ego dan superego yang baik.
Tokoh La Mbatambata dari segi perkembangan kepribadian berada pada fase infantile yang dikuasai pemenuhan prinsip kenikmatan. Ia masih dikuasai oleh alam bawah sadar dan fase id . Ia merupakan tempat dari dorongan-dorongan primitif, yaitu dorongan yang belum dibentuk atau dipengaruhi oleh kebudayaan.
Tokoh Wa Ndiundiu menghimpun seluruh keadaan psikologis dalam dirinya. Fase id (das es) dapat dikendalikan oleh ego (das ich) dan superego-nya (das ueber ich). Tiga kecemasana bersemayam dalam dirinya sekaligus. Eros dan tanatos hadir bersisian dalam reaksi hidupnya. Sebagai seorang ibu dan pemantik permasalahan dalam keluarga, beragam emosi bercampur aduk dalam dirinya dan memengaruhi tindakannya yaitu rasa bersalah, hukuman pada diri sendiri, rasa malu, kesedihan, tetapi dibalut dengan cinta sejati.
Adapun rekomendasi atas penelitian ini adalah agar penelitian mengenai “Wa Ndiundiu” ke depan dapat diitensifkan lagi terutama pengkajian dari segi sisiologis dan antropologis. Dongeng “Wa Ndiundiu” harus diajarkan di sekolah-sekolah pendidikan dasar dan menengah khususnya di Kota Baubau, agar siswa dapat memetik hikmah dan pesan besar yang terkandung di dalam cerita. Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara diharapkan dapat lebih progresif di dalam melakukan pengkajian, penelitian, dan pemetaan sastra lisan di Sulawesi Tenggara, khsusunya yang ada di wilayah geobudaya Buton.
5. Daftar Pustaka
Agustina, Pera. 2014. “Psikologi Kepribadian Tentang Teori Sigmund Freud”. Makalah. Universitas Lampung.
Ahimsa Putra, Heddy Shri. 2006. Strukturalisme Lesi-Strauss Mitos dan Karya Sastra. Yogyakarta: Kepel Press.
Amriani, H. 2011. ”Refleksi Sirik dalam Cerita Ana’ Turusienngi Pappasenna to Matoanna”, Sawerigading Vol. 17, No. 2, Agustus 2011, hlm. 304. Makassar: Balai Bahasa Ujung Pandang.
Asrif. 2015. Pengurus Asosiasi Tradisi Lisan Pusat. Dikemukakan saat Diskusi Kegiatan Pembekalan Metodologi Penelitian Sastra, di Gedung Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan yang menghadirkan Melani Budianta sebagai pembicara tersebut, dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara, tanggal 11—12 Mei 2015.
Danandjaja, James. 1994. Folklore Indonesia, Ilmu Gosip, Dongeng, dan lain-lain. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Desyandri. 2014. “Teori Perkembangan Psikoanalisis Sigmund Freud”. https://desyandri.wordpress.com/2014/01/21/teori-perkembangan-psikoanalisis -sigmund-freud/. Diunduh pada tanggal 12 Februari 2015, Pukul 14.24 Wita.
Endraswara, Suwardi. 2003. Metodologi Penelitian Sastra. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
Endraswara, Suwardi dkk. 2013. “Pembentukan Karakter Negatif dalam Cerita Rakyat Terpilih” dalam Folklor dan Folklife dalam Kehidupan Modern. Roshanizam Ibrahim dkk. (Ed). Yogyakarta: Penerbit Ombak.
Freud, Sigmund.2009. Pengantar Umum Psikoanalisis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Husen, Ida Sundari. 2008. “Prosa” dalam Budiman (Penyunting). Membaca Sastra. Magelang: Indonesia Tera.
Mastuti, Yeni. 2014. ”Profil Nabi Muhammad dalam Naskah Gelumpai dan Bazanji”, Metasastra Volume 7, Nomor 1, Juni 2014, hlm. 97. Bandung: Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat.
Miderop, Albertine.2011. Psikologi Sastra. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Moleong, Lexy J. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.
Nurgiantoro, Burhan. 2000. Teori Pengkajian Fiksi. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Tarigan, Henry Guntur. 1984. Prinsif-prinsif Dasar Sastra. Bandung: Angkasa.
Stanton, Robert. 2007. Teori Fiksi Robert Stanton. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
Suryabrata, Sumadi. 1988. Psikologi Kepribadian. Jakarta. Rajawali Pers.
Susanto, Dwi.2012. Pengantar Teori Sastra. Jakarta: Caps.
Udu, Sumiman dkk. 2005. “Cerita Rakyat Buton dalam Prespektif Gender”. Laporan Penelitian. Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara.
Literasi Kopi dari Festival Indonesia Membaca, Karawang
Kabupaten Karawang diserbu buku dan penggiat literasi dari berbagai pelosok Indonesia. Festival Indonesia Membaca (FIM) telah dibuka pagi tadi. FIM berlangsung mulai 21—25 Oktober 2015. Arak-arakan peserta, terutama dari setiap kota dan kabupaten di Jawa Barat, berjalan dari kejauhan menuju panggung utama FIM. Kesenian daerah khas Jabar yang mengiringi arak-arakan yang sebagain besar dibalut baju berwarna hitam, menjadi sesuatu tontonan yang langka bagi saya. Magis dan religius! Puluhan tenda berdiri untuk menjadi rumah literasi dari seantero Jawa Barat. Lalu ada tenda utama yang menghimpun proses dan kegelisahan kreatif penggiat keberaksaraan dari berbagai daerah di tanah air. Ada panggung diskusi di dalamnya yang menampilkan penulis, penggiat sastra dan gerakan membaca dari berbagai Taman Bacaan Masyarakat di Indonesia. Buku, majalah, jurnal, CD, dan sejenisnya dibagi secara cuma-cuma bagi pengunjung. Usai pembukaan FIM, Firman Venayaksa sebagai Presiden TBM Indonesia tempail dalam sesi diskusi yang menarik. Kran-kran literasi harus segera dibuka di setiap pelosok, katanya. Forum TBM dan komunitas sastra harus bersinergi menjadikan Indonesia melek literasi, menuju peradaban yang lebih baik, lanjutnya.
Di antara deretan stand TBM, terdapat stand Literasi Kopi yang dijaga dan diasuh oleh Faiz Ahsoul. Sebagai barista, ia melakukan demo meracik kopi biji dalam sebuah alat mungil, yang berujung sebagai kopi pekat di gelas. Kopi biji itu, katanya, dipetik langsung di ladang petani sebagai hulu perkopian dan berakhir di gelas seorang konsumen–dalam racikan barista–sebagai hilir penikmatan.
Sebagai gerakan literasi, peracikan kopi adalah sebuah proses memberi dan mendapatkan knowledge, pengetahuan. Penikmat akan mengetahui cara menghargai, proses meracik, dan menikmati kopi. Sebelum sebuah tegukan sampai di ujung lidah konsumen, ia akan tahu betapa “pahit” perjuangan seorang peladang kopi dalam menanam dan memelihara kopi. Meracik kopi dalam tangan seorang barista adalah meracik kehidupan itu sendiri.
Demikianlah, sehingga seteguk demi seteguk kopi dari racikan sang barista, Faiz Ahsoul, telah memasuki kerongkongan setiap pengunjung yang sudah mulai kering akibat musim kemarau berkepanjangan. Beberapa teguk, sang kopi juga telah membasahi kerongkongan saya.
Faiz memberi tips mereguk kopi. Saat kopi sudah berada di gelas, jangan langsung diminum. Tunggu ia agak reda dari panas, lalu kemudian sentuh ia pertama kali dengan ujung lidah (mungkin ini semacam penghormatan kepada kopi). Selanjutnya, regukan pertama tahan ia di dalam mulut, lalu berkumurlah dengan kopi, biar seluruh bagian dalam mulut merasakan citarasnya. Setelah itu, lanjutkan ia ke dalam kerongkongan, lalu ke dalam perut. Memang berbeda. Usai saya praktikkan tips tersebut, citarasa kopi tetap melekat di dalam langit-langit mulut dalam jangka yang tidak pendek.
Hanya saja, ada satu kebiasaan yang harus saya tunaikan, karena aroma kopi yang melekat itu, mengundangnya minta ditunaikan juga yaitu rokok! Ah, kopi dan rokok seperti sepasang kekasih yang tak ingin diceraikan.
Di sinilah letak seorang penyeduh kopi biasa dan seorang barista yang melek literasi, Faiz, yang bergiat di i:Boekoe, selain tangannya bekerja, juga mengomunikasikan hal-ihwal yang berkenaan dengan dunia kopi yang filosofis dan kontekstual. Ia lalu menamakan kerjanya sebagai Literasi Kopi.
Apalagi, jika kita meniliki ke belakang, kopi identik dengan perjuangan literasi. Para pemikir mendiskusikan gagasannya, sambil menyeruput kopi yang setia menemani. Kopi merangsang otak merangsang pemikiran.Bisa kita bayangkan, dalam setiap racikan seorang barista, dalam setiap regukan seorang penikmat kopi yang gelisah, di antara diskursus kehidupan, lahir gagasan yang brilian, yang di kemudian hari ikut menentukan keberlangsungan hajat kemanusiaan. Hhmmm, literasi kopi memang menarik…
Saya telah menikmati kopi racikan Faiz Ahsoul. Saya ingin menghikmati sesuatu yang sosoito, yang lain, dari Karawang: Goyang Karawang. Siapa tahu, ia dapat menginspirasi saya menjadi Goyang Literasi.
Karawang, 22 Oktober 2015.
Di Lantai Dua Sebuah Kafe, Baubau
Kemarin Magrib, 8 Oktober 2015, usai mengantar Camar Wakatobi ke rumahnya di Baubau, saya dan La Yusrie menemui seseorang yang tengah menanti di lantai dua sebuah kafe di seputaran Pantai Kamali. Duduk di pojok ruangan menghadap ke Teluk Buton, kami langsung menyalaminya. Yah, dia adalah Yusran Darmawan, seorang intelektual muda yang lagi bergairah dan dunia pengelanaan, menjemput pengetahuan dan pengalaman lapangan. Penulis yang menayangkan karyanya melalui laman http://www.timur-angin.com/, baru saja menutup laptopnya, mengakhiri sebuah tulisannya. Dia lalu berkisah tentang Buton, politik, dan pengembaraannya lantas mengeluarkan sebuah buku “Membangun Indonesia dari Pinggiran” yang ia tulis bersama dua temannya yang lain. Sebuah buku yang memotret pekerjaannya mendatangi pulau-pulau terluar Indonesia, memberi sentuhan kepada masyakarakatnya. Lalu Yusri menyambung dengan misinya di dunia politik dan kebudayaan kontemporer di Buton, khususnya Buton Tengah, sebuah daerah otonom baru. Saya menyambut dengan cerita tentang gerak maju dunia sastra di Kendari dan Sulawesi Tenggara. Yusran menyeruput kopi coklat sambil memandang pelni yang perlahan meninggalkan Dermaga Murhum. Yusri menarik jus apel ke kerongkongannya sambil memposting sebuah status di facebook, lalu saya mulai memetik kata-kata di udara.
Angin Magrib Pasar Kembang
:untuk Koto dan Thendra

Pasar Kembang, Yogyakarta. (Sumber: http://www.hipwee.com)
Angin Magrib menggeleparkan bau hitam
Membopong kami ke arus malam
Yang berdengung dan berapi
Di lorong-lorong fana, dewa dewi
Laron-laron putih, kumbang-kumbang abu
Membakar udara, menandaskan diri dalam pesta
Rambut cemeti membetot betis Itali
Ditangisi ranggasan jalan yang papa
Badan dan gairah terebus rayu, botol dan kata beradu
Pecah, melukai punggung malam yang basah dan rawan
Aduh
Sebuah lecutan membabat jantung
Irisan senar meronta di daging tulang
Tubuh kami ranggas sepanjang api
Terkapar mendidih dalam lumpur matahari
Angin Magrib Pasar Kembang
Menggeletar ke jasad Malioboro
Rambut kami dirambati kabut begadang.
Lalu sekuntum mawar berbau Pepsi menggoda, hello
Kami meramal langit Yogya yang abu
Terharu diberondong mata biru
Di tengkuk trotoar, terbenam jejak seorang sufi
Terbentur di dinding puisi, dibopong dewata Bali
Kami berzikir di pasar samar
Berdoa di antara botol Magrib dan tarian Isa
Adakah gugur hujan badar
Kami berkendara keranda
Melaju ke pemakaman Sleman
Angin magrib jatuh
Tersedu di pintu subuh
Selamat pagi
Yogyakarta-Kendari, 2009
Haiku 1
Jelajah Kota Jelajah Kata: Memasuki Kota Lama, Kendari
Foto Perjamuan Sastra, Diskusi Buku Ritus Konawe karya Iwan Konawe
Membaca Ritus Iwan Konawe
Oleh: Syaifuddin Gani
/1/
Hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah selamat bagi Iwan Konawe karena buku puisinya, Ritus Konawe, berhasil masuk dalam nomine 15 besar buku puisi, Hari Puisi Indonesia yang dilaksanakan oleh Yayasan Hari Puisi Indonesia di TIM, Jakarta, 8 September 2015 lalu. Bagi Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, ini adalah sebuah berita yang menggembirakan karena telah mengangkat dunia sastra, khusunya puisi di daerah ini dalam perbincangan sastra Indonesia. Oleh karena itulah sehingga malam ini, Jumat, 18 September 2015, kita diskusikan kembali Ritus Konawe.

Diskusi di Rumah Pengetahuan, 18 September 2015. Dari kiri: Ari Ashari, Deasy Tirayoh, Syaifuddin Gani.
/2/
Bagi saya, membaca puisi bukan lagi membedah dengan maksud menemukan intisari pesannya, tetapi ibarat memahat tafsir atasnya. Jika membedah puisi diibaratkan menggunakan pisau untuk merobek-robek daging puisi lalu menemukan “jantung” utama makna, maka memahat puisi diibaratkan menggunakan pahat untuk mengukir tubuh makna. Demikianlah, sehingga dengan melakukan kerja pemahatan, apa yang saya kemukakan dalam tulisan ini adalah sebuah “patung” pemaknaan saya, yang jika dipahat oleh orang lain akan menghasilkan “patung” pemaknaan yang berbeda pula.
/3/
Dalam pengalaman berproses (teater dan sastra) bersama dan membaca sajak-sajak Iwan Konawe yang berlangsung lebih satu dekade (15 tahun) di Teater Sendiri yang dibina oleh Achmad Zain Stone dan pada pergaulan sastra secara luas, saya memang melihat bakat yang kuat dari Iwan. Bakat tersebut, selain pada gairah menulis, terutama pada cipta puisi yang ia lahirkan. Pada antologi puisi Sendiri (I) tahun 2003 yang diterbitkan Teater Sendiri, ia sudah memperlihatkan daya ungkap yang unik dan matang, dengan gaya ironi. Misalnya “dalam lorong-lorong masa/kita bersua/ dalam nyanyian elegi kematian/ kita berduka, dengan nafas tersengal/ dalam etika yang sombong/ kita ahli fikir yang fakir/ dalam lambaian daun mengering/ (Sajak “Ragaku ragamu, tak Pernah Ada Kata Diam”). Lalu, pada antologi Sendiri 2 (Teater Sendiri, 2004) ia menulis: /senjata berperang/ bergegaslah mencari hamba/ di perumahan maha gersangmu/ berdinding debu istana/ beratap teknologi dewasamu/ (Sajak “Kenangan Malam, halaman 50). Kematangan pengucapan Iwan Konawe semakin tampak pada antologi Sendiri 3 (Teater Sendiri, 2006). Di sana, sudah mulai mengemuka naluri dan kebiasaan petualangannya ke berbagai kota dan kampung di Sulawesi Tenggara maupun di berbagai kota Indonesia, baik karena memang diniatkan, maupun karena “dinamika dan masalah” dari rumah maupun oleh komunitas tempat ia berproses, dalam semangat eksil. Lihatlah sajaknya yang berjudul “Kembali Ia akan Memintal Waktu”, halaman 78, yang ia tujukan untuk TS (Teater Sendiri):
Telah ia sepuh segala
Suka serta duka
Cita serta cinta
Di gedung besar sana
Sebulan, ia kenang lampau yang meriak
“Sembari pamit kepada malam yang pahit berarak
Kuteteskan pula setetes bening di kelopak
Bukan karena bara dada telah menetak
Tapi kesabaran mesti kudendangkan kendati telah retak”
Bait kedua di atas adalah semacam solilokui penyair bahwa ia akan “pamit” bagi komunitasnya, Teater Sendiri, dan kawan-kawannya karena “kesabaran telah retak”, meskipun harus menetes“ bening di kelopak”. Wan Anwar dalam pengantarnya (Sendiri 3: 2006) menulis bahwa “di antara penyair dalam buku ini, Irawan Tinggoa (nama lain Iwan Konawe, pen) menunjukkan hasrat besar merespoms banyak soal dengan pendekatana tradisi lokal. Kepekaannya pada momen dan hasratnya untuk “mengucapkan” tradisi berpotensi untuk melahirkan sajak-sajak sederhana tetapi mendalam”.
/4/
“Puncak” pencapaian Iwan Konawe adalah ketika sajak-sajaknya dikumpulkan dalam antologi tunggal Ritus Konawe (Framepublishing, Oktober 2014). Iwan Konawe memperlihatkan “kemungkinan Tolaki (Konawe) bagi puisi” yakni bagaimana ia mempersepsi Tolaki dan tradisinya sebagai ibu kandung kebudayaannya menjadi tema utama sebagian sajaknya. Selain Tolaki (Konawe) sebagai suatu etnis, Iwan Konawe mempersembahkan beragam tema yang disuguhkan dengan daya ungkap yang menarik.
/5/
Kekuatan Ritus Konawe paling tidak pada tiga hal. Pertama, ia mampu mengusung lokalitas Tolaki (Konawe) menjadi salah satu tema utama puisinya, sebagaimana yang saya sebutkan sebelumnya. Tolaki sebagai tema, bukanlah sebuah nostalgia romatis, puja-puji, dan sebentuk kecengengan sentimental, tetapi segugus pembacaan yang kritis dan kontemplatif yang menyasar kepada dunia mitologis dan ideologis etnis Tolaki. Ia juga bukan sebagai tempelan lahiriah belaka. Kedua, Ritus Konawe juga mengenalkan sebuah tema yang jarang atau bahkan untuk pertama kalinya mendapat tempat dalam dunia perpuisian Indonesia yaitu tata caha seni pertunjukan. Iwan Konawe sebagai penata cahaya dan artistik seni pertunjukan yang ia dapatkan dan praktikkan di Teater Sendiri dan berbagai komunitas di Sulawesi Tenggara, menjadikan profesinya itu sebagai cahaya penciptaan bagi puisinya. Ketiga, Iwan Konawe memperlihatkan keterampilan berbahasa yang matang sehingga mampu menawarkan daya ungkap yang segar.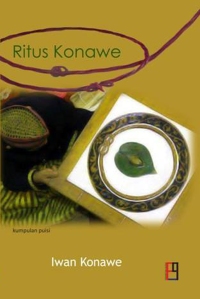
/6/
Saya kembali kepada lokalitas Tolaki. Iwan Konawe tidak terhenti menjadikan Tolaki atau tradisi sebagai tema belaka, tetapi sekaligus sebagai pesan. Tema dan pesan itu berkelindan membentuk nada (tone) sebagaian besar puisi Iwan Konawe yakni rasa rindu pada masa silam, penghormatan terhadap tradisi sekaligus kritis atasnya, dan kecemasa melihat generasi muda Tolaki yang justru menggerogoti tradisi Tolaki. Tema, karena sang penyair memang banyak menulis mengenai Tolaki dan tradisinya. Pesan, karena Tolaki bagi penyair adalah sekelumit tanda budaya yang harus diberi pembacaan atau pengucapan ulang. Kutipan sajak “Andabia dan Aku Terbakar” (Hal. 1) menunjukkan hal tersebut:
Apakah angin senja yang datang dari barat
Serta dari kabut hujan yang berlalu ke utara
Akan menyembulkan setumpuk kenangan purba
Yang terkubur di kaki jembatan Anggaberi
Di palung jantung Kumapo Dahu dan di lingkaran
sukma kalosara
Bagi Iwan Konawe, “Kalosara” adalah bagian dari “setumpuk kenangan purba”, padahal bagi masyarakat Konawe secara umum, kalosara adalah simbol pemersatu yang sangat dihormati. Tugas penyair memang adalah membaca gejala dan keyakinan yang sudah menjadi umum menjadi keyakinan individual, ketika ia sudah melakukan proses transendenlitas. Sajak “Senja Perak di Puncak Oheo” (Hal. 22—23) memperlihatkan pula kegamangan antara kembali kepada tradisi dan upaya melepaskan diri darinya. Berikut kutipannya: /Oheo, anak purba, persembahan dari langit// Lembah hutan begitu teduh, tapi udara begitu membara, di lengkung dada pantaimu, selendang anaway menjadi bianglala/ Sungguh Oheo, perjumpaan kita bagai butiran pasir/ Sejenak menepi ke pantai, lalu kembali terbawa ke lautan Banda/. Oheo sebagai representasi dunia mitologi Konawe (mitos) mendapat “perlawanan” kritis dari penyair dengan membentangkan alam realitas sebagai buah dari tafsir akal budi (logos) yaitu “lembah hutan begitu teduh, tapi udara begitu membara”. Oheo dalam mitologi Konawe adalah pencuri selendang Anaway Ngguluri ketika mandi bersama enam bidadari lainnya. Di kekinian, Oheo adalah sosok mitologis yang dihargai masyarakat Konawe. Akan tetapi, sebagai penyair, Iwan Konawe melihat Oheo sekadar “perjumpaan kita bagai butiran pasir”. Iwan Konawe melakukan kerja tafsir, sindiran, kritik berganda, yakni kritik terhadap mitos di dunia Tolaki-Konawe yang masih menyelubungi alam pikir, yaitu dengan cara kerja akal budi, keberaksaraan, rasio (logos).
/7/
Iwan Konawe melihat tradisi Tolaki, meminjam salah satu larik puisinya “dalam sendu bait”. Ia sendu dan cemas melihat kerapuhan tradisi dan ketiadaan peduli generasi muda. Kecemasan menjadi semacam respon naluriah penyair yang mengedepan ketika menghadapi tradisi. Kecemasan (anxiety) dalam pandangan psikoanalisa Sigmund Freud, adalah akibat dari suatu tanggapan atas realitas yang mengancam. Dalam sajak “Tabere”, Iwan Konawe melihat salah satu simbol adat Tolaki itu sebagai “menjulur kaku ke lantai, digerogoti sepi”. Dalam keadaan “kaku” dan “sepi” itu, bahkan “jarum patah dan sedikit sisa darah menghitam, bersama kursi berdebu, bersama putaran roda mesin jahit yang diam”. Sebagai aku di luar sajak, dalam struktur kepribadian Sigmund Freud, Iwan Konawe berposisi sebagai superego, sebagai suara moral Yang Lain (the other, si liyan), yang patut didengar oleh Orang Tolaki.
/8/
Uniknya Iwan Konawe melakukan kerja metaforis yang indah untuk mengamsalkan kerja menjahit Ina sebagai “menjahit barisan silsilah yang hampir putus, menjadi barisan makna perca-perca kain”. Strategi ini menjadikan puisi Iwan Konawe memiliki keindahan sastrawi yang mumpuni dan mengejutkan karena baginya apa yang dilakukan Ina adalah bukan sekadar menjahit kain-kain aneka warna menjadi Tabere, tetapi yang utama adalah ia “menjahit silsilah” suku Konawe yang yang hampir putus. Pemaknaan yang bermula dari yang fisik ke nirfisik. Ina sebagai keadaan manusia yang sudah uzur adalah lambang kerapuhan tradisi Tolaki.
/8/
Sajak “Ritus Mosehe” (halaman 89), Iwan Konawe mendeskripsikan proses Mosehe sebagai salah satu ritual suci di Tanah Tolaki. Pada bait kedua, penyair mengemukakan sisi lain yang getir dari asal-muasal Mosehe seperti kutipan ini:
Perlahan pabitara menyentuh sukma
Tembangkan makna peribahasa:
“ni ino saramami”
Bukan mantra basabasi
Hanya petuah temurun
Yang masih utuh walau guntur menggemuruh beruntun
Sepejam mata
Taawu dihunuskan
Kerbau putih sebagai simbol tumbal
Darahnya bercecer mengusir sesal
Ia lemas telah mengusir tikai
Yang tak padam
Konawe, 2004
Ia mengatakan bahwa “ni ino saramami” adalah bukan mantra basa-basi, hanya petuah temurun. Ungkapan tersebut adalah gaya bahasa yang mengandung ironi terselubung dan lembut, tetapi berisi kritikan yang menyentil. Hal yang tak kalah ironinya adalah kerbau yang “lemas mengusir tikai, yang tak padam”. Jadi bagi penyair, meskipun Mosehe diikhtiarkan dan kerbau dipersembahkan akan tetapi “tikaian” sesungguhnya tidak pernah padam. Mosehe mengekalkan pertikaian! Di sini, kata “tikai” bermakna luas dan dalam. Tikai tidak lagi bermakna perang fisik semata, tetapi segala hal ihwal negatif yang terkait dengan dunia politik, sosial, budaya, dan seks. Masalah yang membelit masyarakat pascakolonial mendapat kritikan yang tajam dari penyair.

Dari kiri: La Ode Gusman Nasiru, Masjaya, Ahid Hidayat, Wa Ode Nur Iman, Deasy Tirayoh (diapit dua anaknya).
/9/
Dari penagalaman membaca sehimpun sajak-sajak Iwan Konawe yang bertema lokal Tolaki, hal sublim yang saya dapatkan dari upaya memahat tubuh puisinya untuk meraih maknanya, tersimpul dalam beberapa pertanyaan: apakah dan siapakah sesungguhnya yang dipertahankan atau diabadikan? Apakah perang atau Mosehe? Siapakah yangmengabadikannya? Apakah Mosehe telah mengabadikan dan memberi jalan bagi kelahiran perang dan perilaku menyimpang lainnya, atau justru perang dan perilaku negatif itulah yang mengabadikan kehadiran Mosehe? Masyarakat Konawe terbelit sendiri dalam sengkarut tradisinya. Sajak atau puisi, memang tidak berpretensi memberikan fatwa dan khutbah. Di sinilah watak keberadaan puisi dan sastra secara umum yaitu watak simbolik. Ia memberikan lapangan tafsir dan kemungkinan bagi pembaca untuk melakukan pemaknaan yang luas dan beragam. Dalam hal ini, Iwan Konawe telah mengambil peran pembacaan ulang bagi tradisinya.
/9/
Iwan Konawe adalah seorang penyair yang menyukai perjalanan. Perjalanan tersebut bukan semata untuk mendapatkan kepuasan lahir sebagaimana seorang turis. Ia berjalan dalam gairah seorang penyair. Salah satu sajaknya yanag saya sukai adalah “Enam Pecah Batu” (Halaman 84—85) yang seolah-olah adalah representasi petualangan dirinya. Saya akan bacakan secara utuh:
Enam Pecah Batu
Tuan beri aku
Patahan-patahan kata
Sebagai tanda cinta
Katamu, “Carilah enam pecahan batu
Untuk kau tancapkan membatu
Di getir kalbumu”
Seraya menggiring
Petualang
Menyusuri jejak tradisi tabuhan gendang
Menyusur jejak sejarah yang hampir petang
Kaki-kaki melimbang
Merayau di berang kota dan ramah desa
Tak hentinya kurayapi gua-gua cinta
Yang terselubung di dasar pikiran mereka
Mereka-reka letak pecahan batu
Bersemayam jantungnya
Jauh ke dalam, ke palung hati yang tak dapat kuselami
Ataukah berserak di tempat lain
Di pesisir pantai raga yang sunyi
Di ujung jalan, pada jeda azan dan iqamah magrib
Dua pecahan batu
“Kesabaran kalbu
Dan selamat jalan angkuh”
Kudulang dari pecahan beling amarah
Orang Kendari
Persinggahan orang-orang berwajah timur
Satu pecahan batu selanjutnya
“Perenungan sukma pada malammalam suka duka”
Menjadi partitur batin dari geriap kerinduan cinta
Di Uepai
Satu pecahan batu yang lain
Bertebaran di siluet senja sepanjang dermaga
Mekongga—Sorume
Dan anyir birahi pantai Tamboli
“Berikan apa yang kau miliki, meski sebenarnya kau tak rela”
Berikutnya lagi
Pecahan batu yang lain
“Persaudaraan jadilah sebenarnya saudara”
Kurasakan pada pusar perjumpaan
Manusia dengan dirinya
Di setiap hari raya
Satu pecah batu
Tergolek di buih-buih ombak pantai
Topejawa–Makassar
“Suatu waktu, sungai darah dalam tubuh mereka mengering
Hendaklah darahmu menjadi air untuk mereka”
Jalanan lindap
Semangat mulai lingsir
Enam pecah batu terus kubawa berlalu
Berkembara di perbukitan
Di gunung-gunung masa depan
Berluruhan satu-satu

Dari kiri: Rahman Kine, Iwan Konawe, Iwa Maal, Firman S, Djagur Bolu, Achmad Zain Stone, Najamuddin, Al Galih.
Kendari, 2004
/10/
Hal yang menarik dari sajak tersebut adalah “enam pecah batu” merupakan amsal atas enam ajaran filosofis yang ia dapatkan dalam proses perjalanan, proses eksil, proses terbuang. Enam ajaran filosofis itu ia dapatkan tidak hanya di wilayah geososial-budaya Sultra, tetapi sampai di Sulawesi Selatan. Enam pecah batu tersebut adalah intisari empati terhadap manusia dan kemanusiaan serta upaya mematangkah spritualitas diri. Pecahan batu pertama: “Kesabaran kalbu”. Pecahan batu kedua: Selamat jalan angkuh”. Pecahan batu ketiga: “Perenungan sukma pada malam-malam suka duka”. Pecahan batu keempat: “Berikan apa yang kau miliki, meski sebenarnya kau tak rela”. Pecahan batu kelima: “Persaudaraan jadilah sebenarnya saudara”. Pecahan batu keenam: “Suatu waktu, sungai darah dalam tubuh mereka mengering, hendaklah darahmu menjadi air untuk mereka”. Pecahan batu keenam, dengan daya ungkap yang unik bergaya bahasa yang hiperbolis untuk mencapai efek ketragisan humanis, relevan dengan empati kemanusiaa dalam ajaran Islam yakni “Sesunguhnya kaum muslim ibarat satu tubuh. Jika salah satu bagian tubuh sakit, semua merasakannya”. Selain itu, juga mirip dengan ajaran Zen yakni Seppuku atau Harakiri dalam Jepang yakni bunuh diri demi kehidupan yang lain. Bahasa “Suatu waktu, sungai darah dalam tubuh mereka mengering, hendaklah darahmu menjadi air untuk mereka” adalah sebentuk pengorbanan eksistensial yang tragis seorang samurai. Sengkarut persoalan eksistensial yang dialami si aku lirik pada sajak tersebut, bagi Iwan Konawe sebagai aku di luar sajak, adalah upaya untuk “berdamai” dengan dirinya sendiri demi sebuah kemaslahatan.
/11/
Pada Pertemuan Penyair Muda Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara, April 2015 lalu, Raudal Tanjung Banua mengafirmasi apa yang saya tulis sabagai catatan penyunting di buku ini bahwa sebagian sajak Iwan Konawe banyak yang mengetengahkan hal-ihwal dunia tata cahaya pertunjukan, sesuatu yang sangat jarang dirambah dunia perpusisian Indonesia. Pada posisi ini, bagi saya, Iwan Konawe menjadi spesial dalam puisi Indonesia. Ternyata, profesinya sebagai penata cahaya dan artistik teater Sulawesi Tenggara dan beberepa kali pertunjukan seni di Jakarta dan kota lainnya, menjadi lahan subur bagi puisinya. Cahaya bagi puisinya, bukan terhenti sebagai cahaya yang menerangi kegelapan panggung atau sebagai penegas watak aktor belaka. Ia menyasar sudut lain, di luar dari realitas dan panggung pertunjukan. Sajaknya berikut ini adalah salah satunya:
Sutradara dan Lampu
“Naikkan intensitas
Nyalakan par
Beri amber
Siram lagi backlight border
Yah, semut, berangsur-angsur”
Amarah bergelegar
Tersembur dari walky talky yang keok di meja kontrol
Dari sutradara yang digerogoti getir
Ia cemaskan setiap jejak peristiwa adegan
Merisaukan dirinya dengan penonton
Serupa pecatur yang berpikir keras
Lampu-lampu
Laiknya bidak
Dan para pelayan panggung
Layaknya budak
Penonton adalah raja masa depan
GKJ, 2005- 2013
/12/
Bagi penyair, kerja sutradara teater tidak “seindah” dengan lakon pertunjukan. Di sisi lain, sutradara juga digerogoti getir dan kecemasan yang mengelana sepanjang adegan. Di tangan penyair, lampu bukan benda mati, tetapi benda hidup dalam gaya bahasa personifikatif. Katanya “lampu-lampu laiknya bidak” yang menjadi korban permainan sutradara. Begitu pula, pelayan panggung layaknya budak. Bidak dan budak memiliki makna yang relatif sama yakni orang suruhan, objek penderita, demi kebahagiaan orang lain.
Pada sajaknya berjudul “Penata Lampu” penyair menyuguhkan kenyataan lain dari lakon sandiwara. Seorang penata lampu “yang mengejar jalan lakon-lakon satir, dari kisah hidup, selalu menyamar”. Penyair ingin mengatakan bahwa lakon satir di atas panggugn itu adalah sebuah kisah hidup, atau dengan lain kata, sebuah sandiwara di atas sandiwara. Realitas yang kita jejak ini penuh dengan sandiwara, yang lalu dipotret sutradara menjadi lakon sandiwara. Hal lain yang menarik dari sajak ini adalah, ternyata para penonton itu adalah “pemburu hiburan belaka”. Kritik penyair dari sisi ini adalah penonton seni bukan lagi untuk mendapatkan efek katarsis, pencerahan, pembebasan, dan menghikmati pengalaman spiritual tetapi semata pemburu kesenangan belaka. Penonton tak lain dan tak bukan adalah (korban) mesin industri kesenian itu sendiri. Menonton seni sebagai pengalaman, bukan lagi untuk menghikmati yang kudus, tetapi sekadar pelipur hidup yang profan.
/12/
Iwan Konawe telah menghidupkan lampu dari benda mati menjadi manusiawi. Ia memperlakukannya laiknya manusia yang “terbangun dari tidur panjang”. Lampu yang “Di tubuhnya ada anyir karatan kaleng” ia manusiawikan sebagai sosok dengan “masa lalu yang belum hilang”. Rupanya, lampu-lampu yang selalu menyorot setiap lakon di panggung, baik itu tragedi maupun komedi telah membuat sang lampu terbebani peran sang aktor sekian lama. Perosoalan manusia yang diusung ke panggung, menjadi persoalan sang lampu. Atau dengan lain kata, lampu telah menjelma manusia.
/12/
Salah satu sajak Iwan Konawe yang bertema urban adalah “Perawan Gunung”. Menariknya, untuk menulis kota, penyair harus melibatkan pegunungan yakni “ perawan gunung” untuk ikut serta. Di sini, penyair memotret dunia kelam dan bengis kehidupan kota Kendari yang mengorbankan “darah” seorang perawan. Tema “dunia malam” sangat jarang dijamah oleh penyair Kendari, dan Iwan Konawe melakukannya dengan sajak yang indah. Metafora telah menguatkan sajak ini sehingga menghasilkan pengucapan yang unik dan bernas. “Perawan gunung dengan matanya yang api” adalah ungkapan dari kegairahan muda-mudi untuk mencecap dunia malam. Sebuah ungkapan lain yang cukup kuat adalah “bunga kembang yang tumbuh di rok dan bajunya” telah memberikan saya imaji (imajis) yang kuat. Mengapa bunga kembang itu bukan sekadar “motif rok” tetapi “tumbuh di rok”? Diksi “tumbuh di rok dan baju” menjadikan larik ini menjadi multitafsir bahwa bunga kembang itu adalah sindiran bagi nafsu badaniah sang perawan gunung yang bergairah. Dua larik terakhir puisi ini adalah penutup yang sangat kuat, “matanya yang api, dipadamkan dengan kembang roknya yang berdarah”.
/13/
Bagi saya, mengetahui Ritus Konawe masuk dalam 15 besar buku puisi Hari Puisi Indonesia tidak terlalu mengagetkan, karena saya mengikuti proses kepenyairan Iwan Konawe sejak tahun 1999 silam. Ia adalah salah seorang penyair Kendari yang berbakat dengan pengucapan dan tema puisi yang khas. Hal yang mengagetkan bagi saya adalah justru ketidakpercayaannya pada potensi puisinya yang menyebabkan ia hampir hilang dalam kancah perpuisian di Sulawesi Tenggara. Profesinya sebagai penata lampu seni pertunjukan juga hampir mengubur puisinya. Akan tetapi, telah menjadi takdir bahwa sebuah puisi yang bagus akan selalu ditemukan dan menemukan pembaca yang bagus. Siapa yang mencari akan menemukan. Iwan Konawe telah melakukan pencarian yang sedemian rupa, lalu ia menemukan sajak yang pantas dicatat, baik dalam sejarah puisi Sultra maupun Indonesia. Meskipun penyairnya dalam suatu masa tidak meyakini sajaknya, tetapi pembaca yang baik telah menemukan sajaknya dengan penuh keyakinan. Mengenai kekayaan lokalitas dalam sajak Iwan Konawe, saya mengutip pendapat Maman S Mahayana, bahwa “Ritus Konawe menunjukkan semangat penyair mengangkat tradisi sosial budaya masa lalu hadir dengan bahasa puitik. Diperlukan pemahaman tentang sejarah masyarakat dan tradrisi Konawe yang kaya dan eksotik. Menikmati Ritus Konawe membawa kita pada lanskap sebuah masyarakat yang kaya mitos dan spirit sebuah komunitas nun jauh di sana yang pada hakikatnya bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan etnik Nusantara. Sebuah buku puisi yang digarap dengan keseriusan yang mengagumkan. Selamat!”
/14/
Iwan Konawe telah memberi kita puisi. Sejumlah sajak atau puisinya mengangkat tradisi Konawe sebagai tema utamanya. Pada titik ini, Iwan Konawe telah berjasa mengenalkan salah satu etnis di Sulawesi Tenggara bagi pembaca Indonesia yang luas. Selanjutnya, pembaca akan terdorong untuk membaca dan mengenali budaya Tolaki (Konawe) untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh. Selamat untuk Iwan Konawe.
Kendari
Jumat, 18 September 2015































































































